Bau pohon beringin besar di halaman merasuki syaraf olfaktoriku. Aku menarik nafas. Masih dengan ikat pinggang ketat, celana panjang, scarf merah, dan pantofel hitam. Masih dengan segala prosedur yang tertata rapi, sejenak menjelang suara lantang harus disuarakan dan derap sepatu terdengar.
Dari belakang, terdengar langkah sepatu.
"Christopher!"
Aku menoleh. Dan bibirku semakin terkulum rapat, terkunci dalam celah yang seringkali aku sebut kebisuan fana. Padahal itu hanya gengsi, entah kenapa tiap frase tertelan dengan mudah dibawa air ludah ketika ia hadir. Ketika suaranya terdengar. Ia menghilangkan air ludah seperti buah asam, padahal bagiku ia terlalu manis.
"Ya?"
"Hormat, Pak Komandan!"
Aku tertawa. Tertawa di saat grogi adalah cara ampuh untuk menghindari tatap matanya. Matanya agak sipit dan tidak bening, tetapi alur tatapannya fokus dan mudah membuat mentalku jatuh dengan mudah.
"Hormat juga, peserta upacara."
"Nggak penting," Riby tertawa lepas seraya memukul lenganku pelan. Berbondong-bondong siswa-siswi lainnya sudah meninggalkan lapangan upacara, segera pulang tanpa merasakan perbedaan atas peringatan 6 dasawarsa dan 1825 hari. Kebanyakan begitu. Aku pribadi juga merasakan ada hal yang aneh dengan 65 tahun berjalannya nusantara hijau zamrud ini. Seakan semakin bertambahnya umur, semakin terbukalah kebobrokan tanah di atas air yang terapit Pasifik dan Hindia.
"Nggak pulang?" Tanyaku basa-basi.
"Nggak."
"Kenapa?"
"Kamu belum pulang," Ia mengangkat bahu cuek, tanpa sadar bahwa jawabannya sudah membuat intuisiku penasaran. "Jadi ya, aku mendingan nunggu."
Aku kembali diam. Sebenarnya menanyakan alasan Riby merupakan hal menarik tersendiri buatku, tapi aku urung. Aku melihat ke atas, entah mengapa kini sang saka yang terkibar di atas sana seakan menatapiku. Menatapiku seakan aku ini makhluk konyol yang harus jadi pecundang. Pemalu. Orang terakhir.
"Hari ini kamu bete banget sih?"
"Hmm?"
"Kamu bete banget," Ucap Riby lagi. Aku hanya bisa menatap dia heran.
"Nggak ah."
"Kamu memang tertawa, tapi kamu sebenarnya sedang memikul beban berat."
"By, tolong banget deh. Puitis amat. Aku nggak ngerti maksud kamu."
"Suara kamu tadi," Riby bersender pada pohon beringin. Salah satu keanehan Riby, ia suka sekali pohon beringin halaman sekolah yang seringkali dianggap angker oleh kebanyakan orang. Baginya, pohon beringin adalah pohon paling bijak sekaligus dermawan, karena bisa meneduhi terik secara luas. Pusat dari pikiran dingin yang tidak emosional. "Tadi suara kamu memang lantang, tapi entah kenapa rasanya gak mantap. Dan ini nggak mungkin salah, aku mendengar nada getir..."
Kini aku seratur persen menoleh. Dahiku mengernyit tidak suka. "Memang kamu tahu apa?"
"Tahu apa?" Nada suara Riby meninggi. "Tahu bacem!"
Aku tergelak.
"Bukan itu maksudku."
"Aku tau, Chris. Aku tau," Riby mendengus kesal. "Aku tau sekali."
"Tau apa?"
"Tau kamu."
Hening kembali menyulut, tanpa ada semburat panas yang menyapu kulit. Justru beku. Dingin. Seperti lapisan es yang membeku karena tertiup angin utara. Wajahku juga tidak memerah atau tersipu. "Oh."
"Kenapa kamu sedih, Chris?"
"Aku nggak sedih!"
"Kamu sedih!" Balas Riby yakin. "Hanya saja tanpa air mata."
"Kamu nggak mengerti..." Chris berucap gusar. "Sudahlah, nggak layak kita bertengkar di bawah sang saka seperti ini."
"Biar saja," Riby mendongak, menatapi sekelebat kain warna darah dan tulang yang terkibar menghiasi celah antara langit dan awan. "Negaraku ini negara yang selalu bisa menerima kenyataan, Chris. Karena itu, kita bisa bangkit dari kesusahan. Kita nggak pernah pasrah dengan kepahitan, justru dengan kepahitan kita belajar menghargai kebahagiaan. Dan bagi kami, kenyataan membuat perbedaan kami bisa menjadi penyatu. Kamu juga orang Indonesia, kan?"
"AKU BUKAN ORANG INDONESIA!" Balas Chris kesal.
Kali ini Rebecca ganti membisu. Matanya menatap Chris kecewa dan tidak habis pikir. "Kamu masih kepikiran soal akta warga negaramu yang belum diganti?"
"Sampai kapanpun itu nggak bisa diganti selama orang tuaku masih memegang akta warga negara Belanda, By... Aku memang munafik. Dan lagipula, aku memang nggak mau jadi orang Indonesia."
"...Kenapa?"
"Kamu tau kan sulitnya tinggal di negara ini? Bahkan untuk sesuap nasipun kamu harus mengorbankan luka dan memar. Kehidupan yang benar-benar nggak layak. Dan untuk apa aku harus di sini kalau aku bisa tinggal di negara lain?"
"Terus untuk apa kamu dengan beraninya membawa bendera itu, Chris?!" Ucap Riby gemas. "Kalau kamu memang nggak suka Indonesia, kenapa kamu berani membawanya? Kamu nggak layak!"
Nggak mengertikah kamu bahwa aku iri dengan kamu, yang bisa berbangga akan negaramu sendiri? Sementara identitasku terbagi di dua negara yang dahulunya selalu berperang.
"Kamu itu nggak pernah belajar ya, Chris..." Bisik Riby pedas. "Kamu pikir aku senang harus berjuang ke sekolah dengan naik sepeda sejauh 15 kilometer? Kamu pikir aku senang harus tinggal di rumah berpapan kayu yang bisa saja terserap pusaran angin puting beliung sewaktu-waktu? Kamu pikir aku senang memiliki negara yang anak mudanya lebih sering apatis? Kamu pikir aku senang memiliki negara yang surat kabarnya memuat berita-berita memalukan tentang petinggi negara? Kamu pikir aku senang tinggal di negara yang jadi negara paling korup di dunia? Kamu pikir aku senang, senang dengan segala yang aku tinggali sekarang ini?!"
Aku kembali diam. Aku kenal Rebecca sudah selama 6 tahun lebih, dan selama ini Riby selalu menjadi sosok paling nasionalis di sekolah. Selain nasionalis, juga aktif. Ia berjuang untuk berbagai bidang sosial dan berpartisipasi dalam dunia sukarelawan.
"Kamu pikir aku senang mengetahui bahwa kekayaan negaraku tidak dibudidayakan? Kamu pikir aku senang tinggal di daerah yang jadi titik penyatu sirkum pasifik dan sirkum mediterania sehingga punya banyak bencana alam? Kamu pikir aku senang? Nggak, Chris! Tapi aku bangga dengan itu semua. Indonesia nggak layak dibenci." Balas Riby kesal.
"Lo ngerti nggak sih, By. Selama gue tinggal di negara ini, gue suka kesel sendiri dengan bagaimana permasalahan kita nggak pernah selesai. Dan lagipula, kenapa juga lo bangga dengan segala kebobrokan itu. Apa yang lo banggakan?"
"Kita pernah susah," Ujar Riby pelan. "Aku memang kecewa dengan segala yang terjadi di negara kita. Seakan nggak pernah ada titik terang atau jalan keluar atas segala sesuatu. Kita selalu susah, tapi itu yang aku suka. Kita susah bersama-sama. Kita bahagia bersama-sama. Dan hanya kesusahan yang bisa membuat perbedaan antara aku, dan kamu, bisa hilang. Hanya kesusahan yang membuat aku terdidik untuk berjuang. Karena itu aku bangga dengan Indonesia. Dengan segala kesusahannya yang tidak habis-habis, berarti Indonesia tidak pernah berhenti berjuang. Kita ini pejuang, Chris. Walaupun kamu bukan warga negara Indonesia, kamu bagian kami selama menjajaki tanah di atas air ini..."
Angin kembali meniup sang saka, sehingga menutupi sinar matahari yang terik. Aku menghela nafas berat, membiarkan penat menjalar di tubuhku.
"Chris, kalau boleh aku tau," Tanya Riby ragu. "Kenapa kamu mau jadi komandan upacara kemerdekaan Indonesia?"
Aku menarik nafas lagi.
"Karena setiap aku melihat warna merah dan putih di atas langit biru itu, aku jadi teringat akan negaraku, By. Aku jadi teringat bahwa sebenarnya warna bendera kita sama. Aku jadi teringat bahwa sebenarnya tidak selayaknya negaraku menjajah kamu. Aku jadi teringat bahwa banyak yang jadi korban karena keluargaku. Aku jadi teringat bahwa nggak seharusnya aku ada di Indonesia..."
Riby masih memandang dengan penasaran.
"Tapi di sisi lain, aku suka melihat bagaimana semangat baru berkobar setiap kali sang saka ini ada di atas sana. Aku senang bagaimana ia bisa lekat di hati rakyat, dibela sebegitu rupa, padahal ia adalah selembar kain. Aku gembira mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Bahwa kamu sudah merdeka. Dan aku tidak layak lagi menjajah kamu. Dan aku tidak pernah bisa menjajah kamu. Dan aku bisa menerima perjanjian bahwa semua layak bebas. Begitu pula kamu."
Kakiku mulai bergerak, beranjak pergi. Meninggalkan tiang yang menjulang di belakangku. Meninggalkan kemerdekaan bagi Indonesia dan rakyatnya. Meninggalkan seorang Riby untuk kebebasannya.
Dan aku tidak pernah bisa menghentikan cucuran tangis yang mulai mengalir. Bagaimana inginnya aku dilahirkan di negara ini, dimana langit selalu dijunjung dan bumi dipijak. Dengan semangat yang enam puluh lima tahun tidak pernah surut. Dengan dibuangnya bambu runcing dan kelapangan hati yang luas seperti kepulauannya. Dengan keragaman yang tak terhitung tetapi mengucapkan satu bahasa. Dengan kibaran merah dan putih yang bisa menjadi penyatu langit dan awan.
Ternyata, aku juga bisa menjadi bagian dari Indonesia. Maukah kalian menerima aku? Aku tidak pernah ingin terlahir sebagai penjajah. Aku ingin belajar mencintai negeri ibu pertiwi ini, yang memberiku racun pada awalan, dan madu pada akhiran. Maukah?
Bangganya kalian, yang bisa menjadi penyatu bahasa, penyatu 5 pulau besar, penyatu riak ombak dengan garis pantai, penyatu pedas Padang dan manis Jawa, dan mungkin penyatu dunia. Suatu hari nanti, pasti.
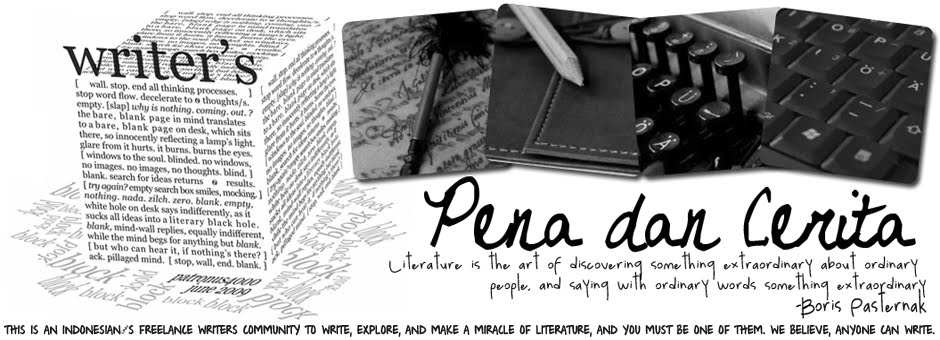

they are both you.
ReplyDelete