
“Akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang pasir.”
Laki-laki disebelahku mengalihkan pandangan dari kertas sketsa-nya lalu menatapku aneh. “Dan pasir itu berupa berlian?”
“Aku serius, Ian.”
Ian terkekeh. “Lalu kenapa? Itu hanya mimpi...atau jangan-jangan kamu ingin pergi ke pantai?”
Aku mendesah. Susah sekali mengajak pria satu ini untuk berbicara dengan serius. “Ian, kalau mimpiku cuma satu kali sih aku juga nggak akan cerita sama kamu. Nah mimpiku ini udah terjadi lima kali dalam kurun waktu dua minggu dan detilnya selalu sama.”
Ian diam bergeming, menunggu.
“Aku melihat diriku sendiri berjalan di sebuah pantai yang pasirnya halus sekali. Aku berjalan bertelanjang kaki, mengenakan gaun putih yang ringan, berjalan menyusuri pantai dengan pandangan kosong dan akhirnya aku menjatuhkan diriku diatas pasir itu. Mau tahu apa yang terjadi?”
Ian mengedikkan kepalanya. Menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak terlalu suka mendengarkan ceritaku.
“Aku berusaha menggenggam pasir yang terus-menerus mengalir keluar lewat sela-sela jariku dan sadar cincin pertunanganku nggak ada.”
Kini giliranku yang diam, menunggu reaksi Ian. Aku ingin memastikan, seperti yang selalu kulakukan akhir-akhir ini.
“Maira, sweetie, kamu lagi-lagi bersugesti. Berhentilah memusingkan mimpi itu. Aku sudah bilang, ini wajar terjadi sama kamu. Calon pengantin wanita selalu berpikir, atau bahkan kayak kamu, mimpi yang nggak-nggak. Aku udah ribuan kali buka buku psikologi dan mencari tahu sebabnya, kamu tahu persis apa sebabnya itu.”
...bahwa setiap calon pengantin baik pria maupun wanita biasanya mengalami hal-hal yang bertentangan dengan pernikahannya, seperti firasat dan sugesti lainnya, padahal itu hanyalah cerminan dari ketidak-siapan seseorang ketika menghadapi hari sakralnya. Aku mengingat rentetan penjelasan Ian dalam pikiranku.
“Ian, sweetie, kamu lagi-lagi menganggap aku bersugesti,” aku membalas kata-katanya. “Do you want me to remind you that we will getting married next week?”
“Jadi? Kamu mau mengaitkan kepanikanmu tentang cincin yang hilang dalam mimpi kamu, dengan pernikahan kita?” Ian melepas kacamatanya. Ia bangkit dari kursi meja kerjanya dan menghampiriku, duduk di sampingku dan membelai rambutku.
“Kalau kamu cerdas, kamu pasti mengerti kenapa wanita lebih sensitif daripada pria.” Aku tahu perkataanku akan membuat Ian tersinggung dan aku memang sengaja mengatakannya.
Benar saja, Ian berhenti melakukan kegiatan yang sangat kusukai dan kembali berkutat dengan sketsa-sketsanya. “Sudah malam. Besok pagi-pagi kita harus fitting baju, ingat siapa yang selalu ngomel tentang acara fitting baju?”
Aku terkesiap, tidak menduga dengan jawaban Ian. Aku bangkit dari sofa hitam yang nyaman itu dan meraih kunci mobilku diatas meja. “Istirahat yang cukup. Aku nggak mau kamu ketiduran pas aku lagi coba kebayanya.”
Kemudian aku meninggalkan apartemen tunanganku tanpa berkata apa-apa lagi.
***
Muhammad Ian Djuanda telah berubah. Berubah sikapnya.
Dulu, ia selalu lembut ketika berbicara denganku. Ia selalu tertawa mendengar omelanku. Ia selalu tersenyum jika kami bertemu. Tatapannya selalu penuh cinta. Sentuhan tangannya selalu membuatku rileks.
Sampai ia melamarku. Apalagi yang harus dilakukan, dari seorang wanita 28 tahun yang dilamar di tengah tumpukan buket mawar putih, selain melonjak kegirangan, memeluk tunangannya dan berkata, “No one could be happy as me!”
Aneh bukan? Sejak lamaran itulah Ian berubah. Ian-ku berubah. Aku yang mengurusi semua persiapan pra-pernikahan. Mencari wedding organizer yang profesional, mengatur undangan, menyusun daftar dekorasi yang akan dipakai dan banyak lagi.
Tapi aku nyaris selalu sendirian dalam mengatur semuanya, seakan hanya aku yang menikah, bukan kami. Yang paling menyebalkan adalah ketika mendengar penjelasannya.
Berkutat dengan sketsa-sketsa desain interiornya.
Sibuk menemani klien mencari bahan-bahan material.
Meracau di telepon setiap hari, setiap jam.
Lupa dengan jadwal-jadwal makan malam rutin kami.
Selalu tidak bisa ditemui di kantor.
Membuatku menunggu di apartemennya yang kosong, sementara ia lupa janjinya untuk mencoba resep baruku.
Hal kecil, hal kecil. Baginya.
“Kamu biasanya selalu ngertiin kondisi aku.” Kata Ian berkilah jika aku mulai protes dengan kegiatannya yang—seakan-akan—menyudutkanku dari hidupnya.
“Apa yang salah dari memintamu, tunanganku, menemaniku memilih bunga-bunga dekorasi untuk pernikahan kita, demi Tuhan?!”
Lalu ia akan memelukku dan meminta maaf. Suara lembut dan harum nafasnya selalu sukses membuatku memaafkannya.
Lalu keesokannya ia akan mengulangi lagi sikapnya. Begitu saja terus selama tiga bulan terakhir. Ia berulah, mengabaikanku, berbicara seperlunya, menjadi jarang menatap mataku ketika berbicara, aku marah dan ia memelukku.
Sampai seminggu sebelum hari sakral kami berlangsung, Ian tetap saja menjadi sosok yang berbeda.
Ada sesuatu...yang harus kutemukan. Sesuatu yang membuat Ian berubah. Entah dari pekerjaannya. Entah sesuatu, atau seseorang.
Tidak. Bukan. Aku bukan mencurigai...aku hanya memastikan.
Dan itu kulakukan saat ini.
***
“Bapak akhir-akhir ini memang sering bertemu seseorang...yang bukan klien kami,” Sissy, asisten Ian, berkata ragu-ragu ketika aku menemuinya di suatu siang, lima hari menjelang pernikahanku. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor Ian.
“Wanita.” Itu pernyataan.
“Saya tidak diizinkan tahu siapa wanita itu. Setiap wanita itu datang, saya hanya ditugaskan untuk memberi tahu Bapak. Setelah itu mereka pergi. Lama sekali. Mereka pernah ngobrol di ruang kerja Bapak dan,” Sissy berhenti sebentar, menimbang-nimbang. “Samar-sama saya mendengar percakapan mereka dan saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari wanita itu. Hanya teman lama Pak Ian.”
Terlihat jelas, Sissy berupaya membuatku tenang. Tapi Sissy salah paham.
“Apa yang mereka bicarakan? Sependengaran kamu?”
Sissy terlihat malu. Malu karena ketahuan menguping pembicaraan bos-nya. “Wanita itu menangis, menceritakan bagaimana ia bercerai—,”
“Cerai?”
“Ya.” Sissy mengangguk mantap.
Aku mengerutkan kening. Menyiapkan pertanyaan berikutnya. “Ciri-ciri wanita itu?”
“Hmm...orangnya mungil, berkulit sawo matang, rambutnya ikal sepunggung warna hitam legam, pakai kacamata dan—,”
“Ada lesung pipit dan matanya sedikit sipit?”
Sissy diam sejenak. Kaget. “Iya, Mbak...”
Aku menahan napas, memutar-mutar cangkir kopiku yang telah kosong, membiarkan Sissy berusaha mencari tahu apa yang sedang kupikirkan lewat mataku.
Aku memikirkan satu nama.
***
Kuamati gedung tinggi di depanku. Akal dan pikiranku begitu saja membawaku ke apartemen Ian malam ini. Aku hanya ingin bertemu dengannya, memeluknya, memperhatikan punggungnya dari sofa hitam favorit kami sementara ia berkutat dengan sketsa-sketsa gambar dari balik kacamatanya.
Aku tidak akan bertanya tentang siapa yang sering ditemuinya. Tentang wanita itu, tentang perubahan sikapnya. Tidak. Aku hanya ingin tangannya membelai rambutku dan aku akan berkata, “Lima hari lagi kita akan menjadi suami-istri.”
Aku melihat mobilnya terparkir di tempat biasa, dan mataku mencari-cari ruangan di tingkat 12. Lampunya menyala, tapi balkon kosong; tanda bahwa ia pasti sedang sibuk bekerja.
Kakiku melangkah gontai, letih. Seharian ini cukup menguras energiku. Di depan pintu kayu kamar apartemennya, aku terdiam cukup lama, memikirkan bagaimana ekspresinya saat melihatku.
Kurogoh kunci cadangan dari dalam tasku dan membuka pintu. Lorong ruang tamu gelap, lalu kulihat seberkas cahaya dari arah dapur. Kulangkahkan kakiku melewati lorong dan menyadari ruang kerjanya kosong dan kampu menyala. Jas dan perlengkapan kerja lainnya berantakan di atas sofa.
Lalu isak tangis. Ada isak tangis. Dari arah dapur.
Bukan isak tangisnya. Ian selalu berada di daftar terakhir orang-orang yang sering kulihat menangis.
“Mai—Maira?”
Isak tangis tadi milik Raras, wanita yang pernah Ian pacari selama 6 tahun dan nyaris menjadi istri Ian. Kepala Raras terbenam di bahu kanan Ian. Lengan Ian yang kekar memeluk erat bahu Raras, seakan Raras adalah boneka kaca yang rapuh.
Ian langsung melepaskan pelukannya, kemudian Raras menoleh. Kami saling bertatapan. Membisu.
***
“Halo, Raras. Halo, Ian. Senang bertemu kalian. Kok reuni nggak ngajak-ngajak?” aku bertanya dengan suara gemetar, tapi bahasa tubuhku kubuat tenang.
“Maira...Maira, ini bukan seperti yang kamu bayangin. Aku—aku hanya...”
“...butuh Ian untuk menceritakan perceraianmu?” aku mengangkat kacamata Raras dari meja makan. “Sudah 4 tahun sejak pernikahanmu. Kamu bahagia selama itu?”
“Maira.” Ian mengingatkan nada suaraku yang mulai meninggi.
Aku tidak peduli pada Ian. “Suamimu memperlakukanmu dengan sempurna? Apa dia mencintai kamu seperti cara Ian mencintai kamu? Aku yakin kamu bahagia sepertiku. Ian bilang kalau lima hari lagi kami menikah?”
Kata-kataku kacau. Ian sekarang berdiri di antara aku dan Raras. Melindungi Raras. Aku bisa melihat matanya mengatakan hal itu.
“Maira, berhenti menyudutkan Raras.”
“Kamu pikir aku menyudutkan? Aku kan cuma mau ngobrol sama Raras. Kamu kenapa, Ian?”
Raras terisak makin keras. “Maira, maafin aku, aku nggak bermaksud kayak gini. Aku kalut...kamu harus tahu rasanya ditinggalkan...dicampakkan...,”
Aku terkekeh pasrah. “Oh, kayaknya aku bakal merasakannya sekarang.”
Raras terbelalak. Ekspresi yang sangat kukenal. “Maira!”
“Maira...,” Ian memelukku. Sialan. “Sekarang berhentilah menyiksa diri kamu sendiri.”
Sekuat tenaga kutahan gejolak kuat dari kedua mataku. “Jujur, Ian. Aku mau kamu jujur. Jujur tentang apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Di hati kamu.”
Ian melepas pelukannya, menatapku dengan matanya yang tajam. Matanya terlihat sedih. Matanya menatap mataku dalam-dalam. Aku tahu apa yang akan ia katakan. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Ia tidak perlu berbicara, tidak perlu menjelaskan. Matanya sudah mengatakan segalanya, juga cengkeraman erat jemarinya di kedua lenganku.
Matanya meminta maaf.
“Aku janji akan terus berada di sisi Raras.”
“Kamu mencintainya.” Itu pernyataan.
“Ya.” Sangat tegas. Sangat khas Ian.
Kulepaskan tangannya, kutatap matanya, kusentuh kedua pipinya...tapi tidak berkata apa-apa.
Dalam bisu, kutinggalkan mereka.
***
Aku sering bermimpi tentang pasir.
Pasir yang menggelitik telapak kakiku. Pasir yang begitu halus, yang seakan-akan selalu menyambut kehadiranku. Pasir dingin dalam genggamanku, yang bulir-bulirnya mengalir keluar dari sela-sela jemariku.
Aku menyukai pasir. Bau asinnya. Teksturnya. Berjalan di atasnya sungguh menyenangkan.
Saat ini aku dikelilingi pasir.
Setelah itu yang kuingat hanyalah bahwa aku mengendarai mobil kembali ke apartemenku. Aku hanya berganti pakaian yang kuambil asal dari lemariku. Kuraih tas tangan kecilku dan hanya memasukkan dompet kedalamnya.
Kuambil secarik amplop putih dari lemari bukuku. Tanpa ragu kulepas cincin pertunanganku dan memasukkannya kedalam amplop. Kutulis alamat apartemen Ian di permukaan depan amplop.
Aku melangkah pelan keluar dari apartemenku. Kutemui satpam penjaga dan menyerahkan amplop berisi cincin itu padanya.
“Saya mau amplop ini sudah diantarkan ke alamatnya besok pagi.”
Si satpam mengangguk dan menatapku lekat-lekat. “Baik, Mbak. Kalau boleh tahu...Mbak mau kemana malam-malam begini?”
Aku diam sebentar. “Bapak tahu dimana saya bisa menemukan pantai berpasir putih dan halus di Jawa Barat?”
***
Gemerisik pasir dalam mimpiku kini nyata.
Desiran angin lembap dalam mimpiku kini nyata.
Gemuruh ombak laut selatan dalam mimpiku kini nyata.
Dan aku dalam mimpiku juga kini nyata.
Aku berjalan menyusuri pola pasir pantai yang tanpa batas, menikmati semilir angin senja sambil menatap guratan-guratan serat awan tipis warna oranye.
Kutinggalkan sepatuku di mobil. Tanganku bebas. Aku tidak membawa apa-apa. Berulang kali kuselipkan helai-helai rambutku ke balik telinga. Gaun putihku yang ringan berkibar terkena angin laut. Aku terus berjalan, berjalan dan berjalan.
Lelah.
Lalu aku berbaring di atas pasir halus itu. Matahari senja menyinariku dengan sinarnya yang beranjak redup perlahan.
Dengan tangan kananku, kugenggam pasir halus itu. Kuangkat genggamanku tinggi-tinggi dan serbuk pasir mengalir keluar dengan mudah dari sela-sela jemariku.
Kuperhatikan jari manisku yang kosong, tanpa hiasan apapun.
Ini mimpiku, mimpiku yang menjadi kenyataan. Bukan aku, tapi memang takdir.
Selamanya pasir ini tidak akan bisa kugenggam sempurna.
“Firasat....”
Firasat segenggam pasir.
Untuk mengenal lebih jauh tentang Astrie Syahrina Ramadhanti Jenie, bisa mem-follow Twitternya di @asyaranie atau membaca tulisan-tulisannya di sini.
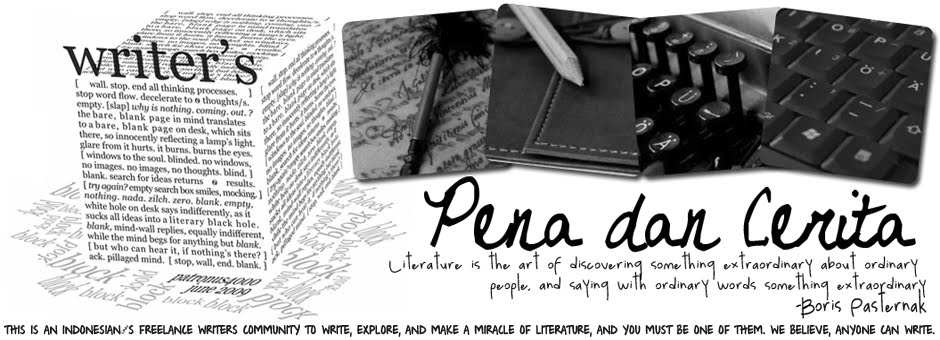
No comments:
Post a Comment