
I don’t remember you looking any better
But then again I don’t remember you...
Sheva, perempuan cantik berusia 20 tahun itu bersenandung kecil mengikuti lagu yang diputar di radio. Tangannya memutar setir dengan lincah, membawa mobil Jazz merah itu melewati jalan-jalan Jakarta yang padat. Pria disampingnya sesekali tersenyum, sepertinya tertular oleh atmosfir easy-going yang memancar dari perempuan itu.
Sore ini terasa begitu cerah dan menyenangkan, seperti sepakat untuk menyambut kedatangan Ara dari New York setelah 3 tahun berjibaku disana.
"So how's New York, Ra?"
"Still the same old glamorous yet sickening city, Senorita...", jawab Ara sekenanya, melempar pandang ke luar jendela. Jakarta juga masih sama, batinnya. Glamor dan memuakkan di saat yang bersamaan. Memuakkan karena orang-orang kaya di dalam gedung bertingkat yang nyaman masih saja tidak peduli dengan anak-anak kecil yang mengemis di perempatan lampu merah demi sesuap nasi. Memuakkan karena kasta itu semakin nyata terlihat; yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terhimpit oleh keadaan.
Sheva melirik Ara sekilas. Cowok itu pernah jadi miliknya, 3 tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, puncak kegiatan-kegiatan konyol masa remaja, puncak kenakalan-kenakalan kecil, puncak segalanya. Tapi Sheva tidak pernah merasa takut melewati semua itu karena Ara selalu disitu untuknya, menjaganya dan memarahinya kalau ia sudah kelewatan. Sebagai pacar, Ara sudah lebih dari cukup. Sheva mengira semua privilege itu; semua perlakuan manis Ara -- konser piano via Skype di kala Sheva tidak bisa tidur, kado ulang tahun yang selalu sampai tepat waktu dan sederet aksi lainnya akan berhenti saat mereka berdua putus, namun nyatanya tidak... seolah tidak ada kata putus yang terucap antara mereka. Kecuali gestur mesra yang dulu sering sekali ditunjukkan Ara, tidak ada yang berubah. Ara masih seperti dulu, dingin dan manis di saat yang bersamaan.
Bahkan setelah 3 tahun berlalu. Setelah semua yang terjadi, kita masih disini. Seperti dulu, persis ketika kita masih berpacaran.
Sheva tersenyum kecil, agak sedih.
"I don't remember you looking any better
But then again I don't remember you..."
"Lagunya sudah habis."
Sheva memutar mata, tertawa melihat Ara yang tampak terganggu dengan lirik yang barusan ia senandungkan.
"Aku suka lagu itu, Ara."
"Aku tidak suka kamu menyanyikannya di depanku. Rasanya seperti disindir."
Sheva menggigit bibir. Kalau ada satu hal yang ia benci dari Ara, itu adalah sifat moody Ara yang benar-benar ajaib. Nyaris mirip PMS; muncul tiba-tiba dan menghilang secepat kilat.
"By the way, Shev... I don't remember you looking any better as well."
Sheva terhenyak.
"Maksudmu?"
"Go figure."
Sheva membuang muka. Sejujurnya ia sudah lelah dengan semua ini. Lelah bermanis-manis di depan Ara, lelah selalu bersikap nrimo pada sikap Ara yang bittersweet, yang tak pernah berubah sejak 3 tahun yang lalu padahal mereka tak lagi terikat dalam suatu hubungan.
Lelah mengikuti permainan yang dikarang Ara dalam hubungan kasual yang tidak jelas ini.
Lelah karena ia masih berharap Ara menyimpan rasa yang sama terhadapnya. Rasa yang tak juga hilang sejak 3 tahun yang lalu.
"Aku capek, Araditya. Let's just end this game, shall we?"
Keduanya bersitatap, sejuta emosi tersirat. Sheva dapat melihat kegetiran dan... rasa rindu? -- tersirat jelas dalam tatapan Ara.
"What if I don't want to?", sahut Ara enteng, tersenyum kecil.
Senyum yang membuat Sheva ingin memeluknya dan menonjoknya pada saat yang bersamaan.
"Lalu mau kamu apa, Ra? Kamu bikin aku bingung, tau nggak?! We broke up, remember? Exes shouldn't be like us -- this whole fake friendship thing is killing me!"
Sheva kini benar-benar menepikan mobilnya, snapped off karena Ara terlihat setenang biasa sementara dirinya sudah kalang-kabut marah begini.
"Whoa, fake friendship?"
Ara mulai terlihat sebal.
"What else, Ra?!"
"Kamu pikir semua yang aku lakukan buat kamu itu cuma buat main-mainin perasaan kamu? Kamu pikir aku nggak tulus ya?"
Sheva kehilangan kata-kata. Pandangan matanya mulai buram.
Oh, crap.
"Lalu apa?", tanya Sheva dengan nada menantang.
Kali ini giliran Ara yang terdiam.
"Karena aku gak mau kehilangan kamu."
Jawaban yang sungguh sederhana namun terdengar begitu rumit di telinga Sheva.
Ara menghela napas sebelum akhirnya melanjutkan,"I can't afford to lose you again, Shev. Kalau aku ngajak kamu balikan..." Ara terdiam sebentar, malu habis-habisan karena ia merasa seperti ABG yang sedang nembak cewek,"lalu kita putus LAGI, aku akan kehilangan kamu. So let's just keep it this way. No bounds, no losing each other, no hard feelings."
Sheva masih menatap Ara, emosi berkecamuk hebat.
"Kamu egois."
***
Malam itu segalanya terasa berantakan bagi Sheva. Harusnya ia dan Ara sekarang duduk berhadapan, di meja pantry-nya yang kecil namun nyaman; saling menimpali cerita masing-masing. Ara dengan solo strugglingnya di New York dan Sheva dengan big step out of her comfort zone: keluar dari rumah keluarga dan pindah ke apartemen atas kemauan dan biaya sendiri -- namun nyatanya, ia kini duduk sendiri di pantry, hanya ditemani secangkir kopi yang asapnya masih mengepul.
Sejak pembicaraan itu berakhir, mereka berdua terdiam sampai Sheva menurunkan Ara di depan rumahnya.
We're done. Really, really done.
Sheva menghela napas, meniup beberapa helai rambut yang terjatuh di depan mukanya. Ia kembali memikirkan kata-kata Ara di mobil sore tadi -- yang setelah dipikir-pikir lagi, tergolong luar biasa karena kata-kata sederhana namun manis itu keluar dari mulut Ara: si kalem yang sama sekali tidak romantis.
Sheva menyesal. Harusnya ia tak semarah itu... harusnya...
Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengontak Ara lagi. Lagipula, bukankah harusnya Ara yang minta maaf? Ia kan butuh kejelasan -- mana ia tahu kalau Ara masih sesayang itu padanya, sayang lebih dari seorang sahabat?
Nasib naksir cowok jenius, batin Sheva sebal. Cowok-cowok jenius memang sudah terkenal dengan kelemotan mereka dalam dunia non-akademis, relationship termasuk salah satunya.
Tapi yasudahlah... mungkin memang aku dan Ara hanya bisa sampai disini.
Gelas kopi yang setengah kosong itu dibiarkan diam di atas meja pantry. Mendingin.
***
Kesenyapan itu terasa begitu menyiksa Ara. Sesuai janji berbulan-bulan yang lalu, Sheva menjemputnya di rumah untuk mengantarnya ke bandara; mengantarnya kembali ke New York.
Mengantarnya menjauhi gadis itu.
Ironis.
Selama perjalanan, Sheva hanya membisu. Aura easy-goingnya lenyap sudah. Melihat wajah judes Sheva, Ara merasa tak punya alasan untuk memancing obrolan basa-basi karena toh Sheva tak akan membalasnya. Paling-paling cuma melayangkan tatapan tajam, tanpa kata-kata. Marah yang sangat Sheva.
Those things should've better left unsaid, anyway, batin Ara kesal. Harusnya ia tidak terpancing ketika Sheva mengulang lirik yang sama dari lagu itu. Lagu yang diam-diam selalu menyentilnya. Lagu yang seakan menyuruhnya untuk segera bend on knees meminta Sheva menikahinya sebelum semuanya perlahan larut dan hilang.
Mereka duduk bersebelahan di bangku diluar ruang tunggu. Lengan mereka bersentuhan namun tak ada yang bicara. Ara pura-pura sibuk membaca koran sementara Sheva asyik menyesap segelas kopi hangat dari Starbucks, ukuran grande sekalian biar mantap. Menurutnya, kopi selalu jadi obat terbaik di saat-saat menyebalkan seperti ini.
"Shev..."
Sheva diam, pura-pura tidak mendengar. Dari tadi kek, batinnya kesal. Malah harusnya dari sebulan yang lalu, sejak kamu dengan enaknya ngomong begitu tanpa penjelasan lebih jauh lagi!
"I know you won't forgive me but I only have one thing to ask to you..."
Sheva memejamkan mata, memberanikan diri untuk memberi jawaban yang ditunggu Ara.
"I'll wait."
Ara tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Hanya itu yang perlu ia dengar; hanya itu jawaban yang ingin ia dengar dari pertanyaannya yang tak sempat selesai.
"...I don't want you to wait, Shev. Not anymore."
Giliran Sheva yang terkejut mendengarnya. Ia sudah mengantisipasi kemungkinan Ara cuma tersenyum lalu beranjak pergi masuk ruang tunggu, namun jawaban ini sama sekali tidak diantisipasinya. Boro-boro diantisipasi, dibayangkan pun tidak!
Suara announcer mengumumkan dengan keras. Ara sudah harus masuk ruang tunggu untukboarding. Tanpa sadar Ara dan Sheva mendengus sebal, merasa si announcer bersuara empuk itu sudah mengganggu sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Sesaat Ara hanyut dalam distraksi si announcer, namun ia cepat-cepat berpaling ke Sheva, memamerkan senyum kecil yang selalu membuat Sheva ingin memeluk dan menonjoknya di saat yang bersamaan. Senyum yang begitu menyebalkan namun juga menghangatkan.
Ara merogoh sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak beludru kecil berwarna merah. Dijejalkannya kotak itu pada kedua tangan Sheva, terkekeh.
"Pake sendiri ya, Sheva."
Ia mengacak-ngacak rambut gadis itu penuh sayang.
"Hei, harusnya kamu yang pakein ini ke aku! CURANG!"
Terkekeh, Ara membalas,"Nanti, Sheva. Enam bulan lagi ya? Nanti aku bawakan cincin beneran..."
Sheva tidak mendengar karena jarak Ara sudah terlalu jauh. Ia membuka kotak itu dengan perlahan, lalu tertawa melihat isinya: sebuah botol kecil berisi miniatur teddy bear (stuffed animal favoritnya walaupun ngakunya ia tak pernah suka boneka!) dalam bentuk clay dan sebuah robekan kertas kecil berisi tulisan tangan Ara.
I'd propose you right away but then I'd miss my flight and everything would be less twisted. Things aren't fun without a little twist, right?
You'll be Mrs. Pramana in 6 months, you better prepare.
Lyrics courtesy of Mr. John Mayer's Who Says.

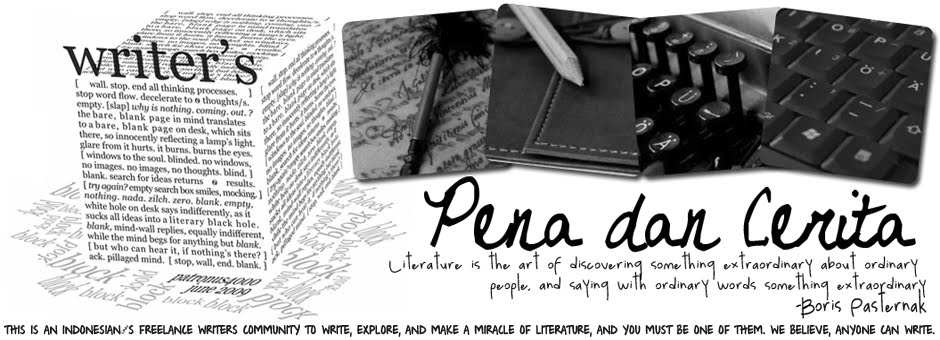
pemilihan kata yang bagus, alur pas, karakter keren, ending buat merinding. go ririn! can't wait ur next post! ;)
ReplyDelete