
Sepotong pagi yang cerah, Juni 2010
Ia menatapku tajam, intens, dan tidak sedikitpun memberiku ruang untuk mengehal nafas. Tatapannya yang intens itu membuatku sadar akan sesuatu. Sesuatu yang selama tujuh tahun persahabatan kami tidak sedikitpun kami sentuh lagi keberadaannya - sebuah obrolan berat.
Damn it, ini terlalu pagi untuk obrolan berat, ujarku dalam hati. Hanya dalam hati.
Aku mohon diri ke dapur, mengambil dua cangkir kopi hitam panas dan sekotak bagelen manis untuk camilan santai. Ia menolak.
Tidak usah kata dia. Cukup aku dan kupingku yang stand-by untuk pagi ini, karena memang dua hal itu yang dia butuhkan untuk menjadi bumbu utama dari percakapan pagi ini. Ini akan jadi percakapan yang berat. Aku tahu sekali, ini akan jadi percakapan yang berat.
Aku mohon diri lagi, mau mengambil tisu di ruang keluarga, kalau-kalau ia tidak bisa menahan tangisnya dan malu untuk mengurai airmata itu didepanku. Lagi ia menolak, katanya cukuplah aku dan kupingku yang stand-by untuk pagi ini. Berat, ini pasti jadi obrolan yang berat.
Berat. Berat. Berat. Ini akan jadi obrolan pagi yang berat karena dia menolak kopi pahit, bagelen manis, dan tisu kering di pagi hari.
Aku mohon diri lagi dan lagi, pamit mau mengambil seporsi nasi goreng yang belum sempat kumakan karena terdistorsi kedatangannya. Ia menarik tanganku, menahan langkahku. Bisakah kau tahan rasa lapar itu? Aku menatapnya, mencari jawaban dari sinar matanya - tapi tidak kutemukan. Baiklah, aku kembali duduk, melupakan rasa laparku.
Ini akan jadi sepotong obrolan di pagi hari yang berat. Berat. Berat.
Aku kembali duduk, menyingkapkan rambutku dan menyiapkan kupingku.
"Ada apa? Kelihatannya sangat berat?" bisikku. Sejujurnya aku kesal. Pagi ini terlalu cerah untuk memulai percakapan yang serius.
"Aku jatuh cinta," ujarnya langsung.
Aku menatapnya bingung campur kesal. Kututupi sebuah binar mata lewat permukaan lensa kacamata geeky yang terpasang manis, tersangah gagah diatas hidungku. Binar kecewa itu muncul belakangan, ketika aku dapat mencerna seluruh perkataan dia.
"Selamat datang di dunia mimpi indah khas orang jatuh cinta!" ejekku agak ketus.
Ia mengelus rambutku, seakan mengatakan lewat bahasa tubuhnya bahwa ia akan tetap jadi dia yang biasanya - tidak akan ada perubahan. Aku hanya mesem setengah kecut.
"Semua kisah cinta tidak selalu seperti Cinderella yang happily ever after. Selalu ada kisah Romeo dan Juliet ditengahnya. Tragis dan menyebalkan!"
"Jangan pesimis," dia berujar sambil tergelak kencang.
"Aku tidak pesimis, hanya realistis," sergahku. "Aku sudah cukup makan asam garam soal cinta, dan aku cukup belajar bahwa Cinderella adalah cerita yang ditujukan untuk anak ABG labil yang sedang meramu kisah cintanya, yang how pity selalu kelihatan bahagia. Tunggu sampai dia ada di episode Romeo dan Juliet, kalau nggak bunuh diri, aku acungin jempol!"
Dia makin tertawa mendengar celotehanku, "Realistis berbeda dengan pesimis, Sayang!"
Sayang? Bukannya barusan kamu bilang kamu sedang jatuh cinta? Kenapa kamu panggil aku sayang?
"Jelaskan dimana bedanya. Dalam kasus percintaan, realistis dan pesimis sama saja buatku!" untuk menghindari merahnya mukaku karena panggilan 'Sayang' darinya barusan, aku malah mengeluarkan nada ketusku.
"Aku tidak mau berfilsafat hari ini--"
Aku menggeleng kencang, kembali menyergah perkataannya, "Dimana bedanya?" ujarku keras kepala.
Dia menarik nafas, tahu bahwa aku sedang tidak bisa dilawan. Dengan sangat sabar, dia menarik nafasnya dan mendekatkan mukanya ke mukaku, "Aku disini, sekarang ini, mau jelasin ke kamu tentang sesuatu yang dimulai dari kejujuran. Kejujuran sama kamu."
Aku menggelengkan kepala kesal, "Arrgggghh! Aku nggak mau dengar soal cinta baru kamu ini. Peduli setan dengan siapa kamu jadian saat ini!"
Ia menarik nafas untuk kesekian kalinya. Tujuh tahun pertemanan membuatnya sangat sangat sabar menghadapi aku. Tapi untuk masalah ini, bagaimana cara membuat aku calm down, aku mengakui ia melakukannya dengan sangat baik. Ia cium keningku, membuatku freezing untuk beberapa saat sehingga ia bisa mulai berbicara.
"Cerita ini diawali dengan kejujuran sama kamu dan diakhiri dengan sikap kamu nanti ke aku, sehabis aku jujur sama kamu."
Aku merengut, "Cepat bilang, deh. Tujuh tahun berteman membuat aku yakin kamu tidak menyembunyikan apa-apa dari aku."
Ia tersenyum, weird, dan aku mendadak kehilangan rasa pede yang barusan keluar. Aku tahu gelatan ini, ia menyembunyikan sesuatu, "Kamu agaknya belum tahu soal ini."
Ya, betul sekali dugaanku, ia menyembunyikan sesuatu.
"Sudah berapa lama membohongiku?" aku bertanya, sok kasual. Langit mendadak cerah, mendadakan ini sudah tidak lagi pagi.
"Sudah cukup lama, sampai aku sadar bahwa seharusnya kamu adalah orang pertama yang tahu mengenai kisah ini," suara dia mendadak bergetar--aku ikut bergetar karena takut. "Aku mau kamu bantuin aku mendefinisikan mana yang baik, mana yang jahat."
Aku mencibir, menahan kantuk dan lapar yang sudah datang sedari tadi. Aku mau mengakhiri saja obrolan ini biar jelas semua.
"Siapa orangnya?" tanyaku to the point. Aku sempat melihat rona kaget diwajahnya ketika ia mendengar pertanyaan to the point-ku. Itu seharusnya bukan menjadi pertanyaan yang frontal. Seharusnya.
"Tidak mau kasih tahu juga nggak kenapa-napa. No big deal," ujarku lagi.
Dia menggeleng, "Bukannya nggak mau ngasih tahu kamu, tapi ini adalah awal dari proses kejujuran aku sama kamu."
Ku kibaskan rambutku, mendadakan aku pusing dengan semua ini, "Omongannya terlalu berat, aku nggak ngerti!" teriakku.
Ia tersenyum, kembali mengelus rambutku dengan brotherly, sambil menepuk pipiku sekali. Suatu rutinitas yang sedari dulu jadi kebiasaan kami berdua. Namun kali ini entah mengapa aku merasa ia melakukannya dengan penuh beban.
"Aku mention satu nama dan setelahnya terserah kamu mau ngapain," ujar dia, akhirnya.
"Try me!"
Ia menatapku, aku menatapnya, terjadi lubang hitam kekosongan antara aku dan dia, dimana itu hanya terisi dengan rasa yang mendadak menyakitkan. Ini obrolan yang berat yang punya akhir yang sama beratnya. Sesuatu menekan-nekan tubuhku, mendadak. Aku seperti ingin terbang, bukan karena bahagia tapi karena................ sakit.
"Budi, Budiansyah Firdaus." kata dia. Kata Putra Hadi Ghian Saputra.
Aku mengeluarkan airmata. Deras, bersamaan dengan perih yang menusuk hatiku intens.

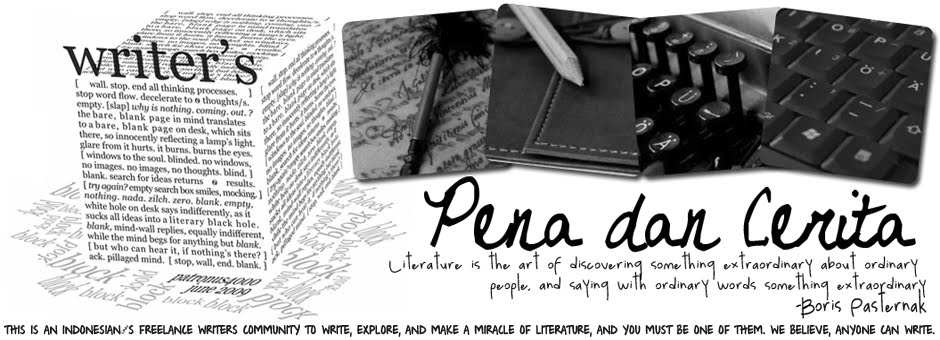
No comments:
Post a Comment