Antares
Aku masih ingat betul, 3 tahun yang lalu, aku memiliki 3 orang sahabat yang sangat berbeda watak. 3 tahun yang lalu, 3 orang tersebut selalu ada bersama-sama denganku. Kami bersahabat - walaupun kami mengambil jurusan serta mata kuliah yang berbeda. Kami bersahabat - walaupun lebih sering bertengkar dan memaki. Kami bersahabat - walau salah satu dari kami sudah hilang.
Kini aku menatap hamparan rumput hijau di hadapanku dengan perasaan tidak keruan. Begitu keruh. Sahabat memang terkadang tidak ada di samping kita untuk selamanya, tapi pelajaran 3 tahun yang lalu membuatku sadar bahwa ada esensi penting dari seorang sahabat, walaupun mereka memang harus pergi meninggalkan kita. Kadang mengkhianati kita, kadang menusuk kita, hanya saja ada alasan mengapa mereka menjadi sahabat kita. Kalau mau jujur, aku tidak akan cocok bersahabat dengan Aldebaran, Rigel, apalagi Altair.
Ingatanku mundur, mengulang kejadian 3 tahun yang lalu. Ketika kami memang harus menjaga bintang kami masing-masing yang saling berjauhan.
“Ya ampun, Res. Santai dikit kenapa?” Ucap Rigel. Rigel memang yang paling slengean dan paling santai di antara mereka – berikut yang paling tidak kenal syaraf panik. Tangan Rigel meraih buku teks Person yang sering ia tenteng, apalagi mendekati hari dimana ia akan segera bergelar Sarjana Ekonomi. Aku tidak pernah bisa tidak prihatin pada otaknya yang seakan sudah kehilangan syaraf ‘warning’ akan bahaya. Bahkan kalau sedang ada kebakaranpun, mungkin hanya Rigel yang akan berkata “Eh, kebakaran lho…”. Sifat kelewat tenangnya itu menyebalkan! Permasalahannya, Rigel selalu dibutuhkan untuk menambah suara dalam keputusan demokrasi – karena Rigel pasti akan ‘ngikut aja’ dengan keputusan bersama. Di sisi lain, hanya dia yang mau mendengarkan cerita nggak penting milikku, Altair, dan Aldebaran. Mulai dari ceritaku tentang energi atom, cerita Altair tentang masa-masa SMP-nya, atau cerita Aldebaran tentang gebetannya yang lebih tua. “Skripsi gue tinggal seperempat lagi kok. Yang lain aja tuh.”
“Yang-lain-aja-tuh? Sial lo, Gel.” Cibir Aldebaran. “Tinggal Altair doang tau!”
“Lo itu gampang panasan ya. Ya… yang lain kan bisa berarti Altair doang.”
Aku makin merengut gemas. Heran, 4 tahun aku berkawan dengan mereka bertiga, aku masih kadang tidak bisa habis pikir bagaimana kami bisa cocok bersahabat. Walaupun dari mereka bertiga memang aku yang lulus paling cepat, dengan IPK 4 dan periode waktu 3 tahun 4 bulan, maka mereka selalu menganggap aku yang paling pintar dari kami semua. Dan karena itu aku ditunjuk sebagai pembimbing skripsi. Yang jelas, menjadi pembimbing Altair, Aldebaran, dan Rigel nggak ada asyik-asyiknya. Sudah tanpa honor, bawel pula.
“Lo itu gampang panasan ya. Ya… yang lain kan bisa berarti Altair doang.”
Aku makin merengut gemas. Heran, 4 tahun aku berkawan dengan mereka bertiga, aku masih kadang tidak bisa habis pikir bagaimana kami bisa cocok bersahabat. Walaupun dari mereka bertiga memang aku yang lulus paling cepat, dengan IPK 4 dan periode waktu 3 tahun 4 bulan, maka mereka selalu menganggap aku yang paling pintar dari kami semua. Dan karena itu aku ditunjuk sebagai pembimbing skripsi. Yang jelas, menjadi pembimbing Altair, Aldebaran, dan Rigel nggak ada asyik-asyiknya. Sudah tanpa honor, bawel pula.
***
Aldebaran
Gue menatapi punggung Antares - si profesor muda yang sedang melamun di hadapan gue. Entah kenapa, mendekati Antares seperti berhati-hati untuk tidak membuat macan mengamuk. Gue menggelengkan kepala.
Kenapa ya gue bisa tahan 3 tahun bersahabat dengan mereka semua?
Mereka nggak spesial. Nggak ada satupun di antara mereka yang eksis di kampus. Bahkan kadang kami suka menamai diri kami sendiri sebagai si kwartet dengan eksistensi nol. Zero existance, Z-ex. Gue yang waktu SMP terobsesi dengan dunia showbiz, jadi agak-agak asing kalau bergaul bersama mereka. Tapi inilah mereka - para orang-orang yang tau bahwa mereka tidak butuh spotlight. They will make their own fame, not find it.
Melihat Antares bengong seperti ini, mencoba menghalau kesedihan yang masih membayangi kita selama 3 tahun, gue jadi ingat keadaan beberapa tahun kami. Kebersamaan kami yang terakhir.
Lagi-lagi Rigel dan Antares ribut. Walaupun kami sudah berumur 22 tahun, kami sering merasa kalau kami nggak cocok disebut sebagai ‘pemuda’. Sifat kami aneh. Antares yang idealis, fokus, dan jenius. Rigel yang santai, mudah setuju, dan jarang membantah. Altair yang teliti, pendiam, dan paling sensitif. Dan gue – Aldebaran, yang bawel dan biang heboh. Di baliknya, kami meributkan hal-hal kecil. Seperti meributkan bahwa makan bakmi lebih enak pakai sambal tauco dibandingkan saos, meributkan kaus kaki siapa yang paling bau, meributkan pilihan game yang akan dimainkan waktu akhir minggu, hingga meributkan siapa yang terus-menerus jadi jomblo. Untuk urusan jomblo, Antares memang selalu jadi pemenang mutlak. Tapi aku tidak peduli – tidak ada dari kami yang tidak peduli. Bagiku, Antares selalu menjadi Antares – sosok yang aku yakini akan sukses di masa depan. Sosok kaku bagai patung, tapi ia berhasil karena ia tahu apa yang ia inginkan. Terlebih, Antares selalu tau bagaimana ia harus melakukannya – dia bertanggung jawab atas hidupnya.
“Altair, kalau lo memang beneran pengin lulus, serius dikit dong!” Ucapku ikut kesal. Berbeda terbalik dengan Antares yang sangat objektif, Altair yang wajahnya paling pucat di antara yang lain adalah yang terhalus. Dia benar-benar pemimpi, separuh dari dirinya dialiri darah seniman murni.
“Gue ada urusan sebentar,” Balas Altair seraya menggeleng kecil. Altair meraih lemari dan mengeluarkan beberapa makanan ringan dari sana dan menaruhnya di atas meja. “Ada satu hal yang kayaknya lebih menarik dari skripsi.”
“Apalah kata lo, Al. Lo suka ngelantur,” Tambah Antares. Tidak salah – dari kami berempat – hanya Altair yang dicurigai memiliki kemampuan tertentu, kemampuan sixth sense dan berpindah ke alam lain saking seringnya ia bengong.
“Santai aja…”
Aku memutar kedua bola mataku. “Gue males juga kalau begini caranya lama-lama,” Baru saja aku berniat pergi dari ruang belajar Altair, ada sesuatu yang menahanku.
“Gue ada urusan sebentar,” Balas Altair seraya menggeleng kecil. Altair meraih lemari dan mengeluarkan beberapa makanan ringan dari sana dan menaruhnya di atas meja. “Ada satu hal yang kayaknya lebih menarik dari skripsi.”
“Apalah kata lo, Al. Lo suka ngelantur,” Tambah Antares. Tidak salah – dari kami berempat – hanya Altair yang dicurigai memiliki kemampuan tertentu, kemampuan sixth sense dan berpindah ke alam lain saking seringnya ia bengong.
“Santai aja…”
Aku memutar kedua bola mataku. “Gue males juga kalau begini caranya lama-lama,” Baru saja aku berniat pergi dari ruang belajar Altair, ada sesuatu yang menahanku.
***
Rigel
"Al?"
"Ssh..." Aldebaran menaruh telunjuknya di depan bibir. "Pelan-pelan. Antares lagi bengong."
Gue mengangguk. Gue tau betul, Antares yang paling memendam rasa sesalnya dibandingkan kami berdua. Antares yang paling merasa bersalah. Sifatnya yang keras dan tidak tolerir kadang mudah disentil, apalagi kalau ia tau bahwa ia sempat bersalah. Gue tau, Antares hanya menyesal akan satu hal. Gue ngerti bahwa dia belum sempat minta maaf sama Altair.
Aldebaran dan Antares sama-sama terdiam. Gue ikutan diam. Habisnya nggak lucu juga kalau gue ngelawak, walaupun gue pengin banget. Awan mendung menghiasi langit di atas kepala gue, membuat gue jadi kepengin ikut-ikutan mendung.
Tapi gue tau, Altair nggak pengin kita bertiga terus-menerus menyesal.
Sumpah, kadang gue capek hati juga kumpul di sini.
“Ayolah, Ran. Sampai kapan sih lo mau terus-terusan ogah ngumpul bareng begini?” Ucapku, masih dalam nada cuek.
“Cih. Lo tau nggak sih, Gel. Kadang gue capek hati harus ketemu sama lo-lo pada,” Tukas Aldebaran dengan raut kesal. Mungkin bukan hanya dia, gue juga kesal dengan tingkah teman nongkrong gue sejak awal kuliah ini. Pada dasarnya memang aneh, kami berempat bertemu karena sama-sama menjaga kios di Festival Kebudayaan bertemakan Jepang 4 tahun yang lalu. Dan kebetulan sekali, kios kami berderet. Gue menjaga kios lampion kertas, Aldebaran menjaga kios takoyaki (Makanan ringan a la Jepang, berbahan dasar cumi atau gurita yang dibentuk menjadi bola), Antares menjaga kios suvenir, dan Altair menjaga kios ikebana (Kerajinan tangan merangkai bunga). Gue masih ingat malam itu, sebelum kembang api dinyalakan, kami mengunjungi kios ramalan. Yang meramal adalah gebetan Antares satu-satunya sejak SMP – namanya Karissa. Waktu itu Karissa mengatakan hal yang sangat unik.
“Ayolah, Ran. Sampai kapan sih lo mau terus-terusan ogah ngumpul bareng begini?” Ucapku, masih dalam nada cuek.
“Cih. Lo tau nggak sih, Gel. Kadang gue capek hati harus ketemu sama lo-lo pada,” Tukas Aldebaran dengan raut kesal. Mungkin bukan hanya dia, gue juga kesal dengan tingkah teman nongkrong gue sejak awal kuliah ini. Pada dasarnya memang aneh, kami berempat bertemu karena sama-sama menjaga kios di Festival Kebudayaan bertemakan Jepang 4 tahun yang lalu. Dan kebetulan sekali, kios kami berderet. Gue menjaga kios lampion kertas, Aldebaran menjaga kios takoyaki (Makanan ringan a la Jepang, berbahan dasar cumi atau gurita yang dibentuk menjadi bola), Antares menjaga kios suvenir, dan Altair menjaga kios ikebana (Kerajinan tangan merangkai bunga). Gue masih ingat malam itu, sebelum kembang api dinyalakan, kami mengunjungi kios ramalan. Yang meramal adalah gebetan Antares satu-satunya sejak SMP – namanya Karissa. Waktu itu Karissa mengatakan hal yang sangat unik.
“Nama kalian berempat cocok,” Ucapnya lembut. “Kalian berempat memiliki nama yang berhubungan dengan rasi bintang.”
“Rasi?”
“Rasi?”
“Ya, kumpulan bintang-bintang yang seringkali menggambarkan keadaan waktu dan langit, pusat dari segala ramalan. Dan kalian berempat benar-benar seperti gambarannya.” Adis tersenyum lagi. “Kamu, Altair. Altair merupakan bintang paling terang yang ada dalam rasi Aquila. Kamu digambarkan juga sebagai burung elang, burung yang dianggap kejam – padahal elang adalah burung yang paling lemah lembut dan rela berkorban. Seekor elang selalu mau menaruh kepentingan kelompok di atas kepentingannya sendiri.” Adis tersenyum lebar. “Altair menjadi satu-satunya yang paling stabil dan menjadi tumpuan segala waktu.”
“Bintang paling terang dalam rasi Taurus adalah Aldebaran. Rasi Taurus dianggap sebagai rasi yang paling berdedikasi di antara semuanya. Taurus juga memiliki garis rasi yang paling cantik – karena itu dewa Zeus bisa jatuh cinta pada Eo, dewi atas Taurus.” Mata Aldebaran hanya bisa mengerjap heran. “Aldebaran, kamu akan jadi motivasi bagi rasi yang lain untuk terus bersinar. Karena kamu selalu jadi sumber sinar.”
“Keh, sebegitu hebatnya ya gue,” Balas Aldebaran pura-pura tidak peduli. “Gimana kalau Rigel?”
“Rigel, Rigel…” Adis meraih satu buah kotak berpelitur unik dari dalam laci. “Rasi yang berderet rapi bernama Orion memiliki bintang paling terang, yaitu Rigel. Orion memang diceritakan telah dibutakan ayahnya – Oenopion. Tapi Orion tetap ditempatkan Zeus di atas segala bintang. Ia boleh buta, tapi sinar Orion tidak pernah mati. Sama seperti kamu, Rigel. Hati nuranimu selalu berkata yang sejujurnya – dan kamu tidak ragu akan itu. Kamu akan menjadi bintang penuntun dalam gelap, karena hati kamu tidak akan pernah buta. Kamu layak berada di atas segala bintang.”
“Rigel, Rigel…” Adis meraih satu buah kotak berpelitur unik dari dalam laci. “Rasi yang berderet rapi bernama Orion memiliki bintang paling terang, yaitu Rigel. Orion memang diceritakan telah dibutakan ayahnya – Oenopion. Tapi Orion tetap ditempatkan Zeus di atas segala bintang. Ia boleh buta, tapi sinar Orion tidak pernah mati. Sama seperti kamu, Rigel. Hati nuranimu selalu berkata yang sejujurnya – dan kamu tidak ragu akan itu. Kamu akan menjadi bintang penuntun dalam gelap, karena hati kamu tidak akan pernah buta. Kamu layak berada di atas segala bintang.”
“Gue nggak gitu kok,” Sergah Rigel malu-malu. “Apa ramalannya Antares?”
Adis menoleh dengan gemulai ke arah laki-laki yang ada di pojok. Antares, sang kalajengking beracun yang menatapnya tajam. Diam-diam, Karissa mengulum senyum.
“Apa yang kamu tau soal scorpio?”
“Beracun.”
“Berbahaya.”
“Nggak ada bagus-bagusnya.”
Antares mendelik gemas pada 3 temannya yang sudah cengar-cengir iseng. Karissa hanya bisa tertawa kecil dan mendeham.
Adis menoleh dengan gemulai ke arah laki-laki yang ada di pojok. Antares, sang kalajengking beracun yang menatapnya tajam. Diam-diam, Karissa mengulum senyum.
“Apa yang kamu tau soal scorpio?”
“Beracun.”
“Berbahaya.”
“Nggak ada bagus-bagusnya.”
Antares mendelik gemas pada 3 temannya yang sudah cengar-cengir iseng. Karissa hanya bisa tertawa kecil dan mendeham.
“Antares menjadi bintang paling terang di rasi Scorpius. Scorpius selalu diplot sebagai antagonis yang misterius dan tidak punya perasaan. Padahal Scorpius adalah rasi yang paling bertanggung jawab akan suatu misi dan masalah. Segala ucapan Scorpius apa adanya, dan ia melakukan apa yang ia lakukan karena Scorpius tau itu benar. Antares akan menjadi bintang pertama, setelah bintang yang paling terang – yaitu Sirius.” Adis menatap Antares yang sudah bengong saking nggak tau mau bereaksi apa. “Antares yang menjadi pelopor, sifat kelamnya yang akan menjadi pendamai. Antares adalah pemimpin.”
“…Tapi serius dikit bisa kan, Al? Lo jangan bikin Antares emosi dong.”
Ucapan Aldebaran membuyarkan lamunan gue. Gue menoleh ke arah Altair yang sudah berdiri tegap di balkon, menatapi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Gue melengos. Tatapan Altair mudah ditebak, semudah menghitung anak sapi. Dan ini tatapannya melambangkan bahwa ia mulai berimajinasi lagi.
Ucapan Aldebaran membuyarkan lamunan gue. Gue menoleh ke arah Altair yang sudah berdiri tegap di balkon, menatapi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Gue melengos. Tatapan Altair mudah ditebak, semudah menghitung anak sapi. Dan ini tatapannya melambangkan bahwa ia mulai berimajinasi lagi.
Altair seharusnya mempersiapkan diri bukan sebagai sarjana lulusan politik, tapi lulusan filsafat. Hobi berpikir yang aneh-aneh – Altair tidak pernah logis. Otaknya seakan berputar dan tidak bisa berpikir satu plot yang sedang terjadi saja. Altair selalu membahas topik yang tidak berhubungan. Mimpi-mimpinya gila, perasaannya terlalu melankolis, dan sifatnya kalem. Padahal kalau menurut ramalan Adis, Altair adalah yang stabil. Kalau orangnya ngelantur begini, apanya yang stabil?
***
Altair
Andai saja gue masih bisa menapaki kaki gue di alam bawah sana.
Andai saja gue masih bisa menapaki kaki gue di alam bawah sana.
Menatapi ketiga sosok yang terakhir kali gue lihat itu bikin gue merasa miris. Andai saja gue masih bisa memohon pada mereka supaya mereka nggak terus-menerus menyesal. Gue nggak ada masalah dengan meninggalkan mereka kok, gue bahkan nggak menyesal belum mengucapkan selamat tinggal. Gue yakin banget, gue akan bertemu lagi dengan para penjaga bintang tersebut.
Heran ya. Kenapa teman-teman gue ini nggak pernah bisa mengerti sedikit saja. Di saat yang mereka pikirkan hanya skripsi, skripsi, dan skripsi – gue memikirkan sebuah kesimpulan aneh dari skripsi dan kelulusan ini.
Setelah lulus, apakah sang bintang akan lebur di langit?
Gue nggak mengerti kenapa gue harus bersahabat dengan Antares yang jutek, atau Aldebaran yang playboy, maupun Rigel yang kehilangan syaraf panik. Cuma ketika tau bahwa mereka memiliki nama bintang – sama seperti gue – gue merasa ini adalah takdir. Kenyataan bahwa ada sesuatu yang harus kita bangun bersama, dibangun oleh keempat bintang ini. Dan gue nggak pengin… bintang-bintang gue pergi begitu aja.
Mereka selalu menganggap gue berlebihan, menganggap gue pemimpi yang bermimpi lebih dari batas kenormalan. Seperti sekarang, di saat mereka sedang sibuk skripsi, apa salah kalau gue mendahulukan urusan pertemanan lebih dulu?
Gue menarik nafas panjang. “Please, lo bisa memikirkan sesuatu yang di luar skripsi sebentar. Gue pusing banget…”
“Kenapa memangnya, Al?” Tanya Rigel. “Lo sakit?”
“Bukan.” Gue menggeleng pelan. “Forgive me for being too cheesy, while talking about friendship. Tapi gue nggak rela lulus.”
“Kenapa? Ini udah saatnya kita menyongsong masa depan,” Tambah Antares tegas. “Karir, keluarga, sebentar lagi kita memulai itu semua, Al.”
“Bagaimana dengan persahabatan?”
Ruangan langsung hening. Gue menatap sahabat-sahabat gue bergantian dengan pandangan sedih. “…Gimana dengan sahabat?”
“Mungkin memang ada waktunya kita harus jalanin hidup masing-masing.”
“Gue nggak pengin sendirian,” Ucap gue. Dengan perlahan, gue menunjuk langit malam bertabur bintang. “Nggak ada bintang yang bisa bersinar sendirian. Kita memang berbeda rasi, tapi kita tetap sama. Kita bintang paling terang dari tiap rasi.”
“Tapi sinar itu,” Antares tetap berucap dingin. “Sinar itu tetap milik masing-masing bintang. Lo harus bisa ngehadapin itu… Gue juga seneng bisa bersahabat dengan lo semua.”
“Lo bertiga…” Gue menghela nafas pendek. “…Punya sinar yang lebih dari sekedar bintang, punya arti yang lebih dari sekedar sahabat.”
Mereka bertiga bertatapan lagi, benar-benar nggak bisa mengerti ucapan gue. Gue melengos dan membanting pintu dengan kesal.
“…Sampai kapanpun kalau rasinya berbeda, nggak akan ada yang mengerti.”
Dalam gelap malam, beberapa tetes air matapun jatuh dari pelupuk mata gue. Gue menggeleng pelan. Gue sadar kalau selama ini, bintang punya lajurnya sendiri-sendiri.
Setelah lulus, apakah sang bintang akan lebur di langit?
Gue nggak mengerti kenapa gue harus bersahabat dengan Antares yang jutek, atau Aldebaran yang playboy, maupun Rigel yang kehilangan syaraf panik. Cuma ketika tau bahwa mereka memiliki nama bintang – sama seperti gue – gue merasa ini adalah takdir. Kenyataan bahwa ada sesuatu yang harus kita bangun bersama, dibangun oleh keempat bintang ini. Dan gue nggak pengin… bintang-bintang gue pergi begitu aja.
Mereka selalu menganggap gue berlebihan, menganggap gue pemimpi yang bermimpi lebih dari batas kenormalan. Seperti sekarang, di saat mereka sedang sibuk skripsi, apa salah kalau gue mendahulukan urusan pertemanan lebih dulu?
Gue menarik nafas panjang. “Please, lo bisa memikirkan sesuatu yang di luar skripsi sebentar. Gue pusing banget…”
“Kenapa memangnya, Al?” Tanya Rigel. “Lo sakit?”
“Bukan.” Gue menggeleng pelan. “Forgive me for being too cheesy, while talking about friendship. Tapi gue nggak rela lulus.”
“Kenapa? Ini udah saatnya kita menyongsong masa depan,” Tambah Antares tegas. “Karir, keluarga, sebentar lagi kita memulai itu semua, Al.”
“Bagaimana dengan persahabatan?”
Ruangan langsung hening. Gue menatap sahabat-sahabat gue bergantian dengan pandangan sedih. “…Gimana dengan sahabat?”
“Mungkin memang ada waktunya kita harus jalanin hidup masing-masing.”
“Gue nggak pengin sendirian,” Ucap gue. Dengan perlahan, gue menunjuk langit malam bertabur bintang. “Nggak ada bintang yang bisa bersinar sendirian. Kita memang berbeda rasi, tapi kita tetap sama. Kita bintang paling terang dari tiap rasi.”
“Tapi sinar itu,” Antares tetap berucap dingin. “Sinar itu tetap milik masing-masing bintang. Lo harus bisa ngehadapin itu… Gue juga seneng bisa bersahabat dengan lo semua.”
“Lo bertiga…” Gue menghela nafas pendek. “…Punya sinar yang lebih dari sekedar bintang, punya arti yang lebih dari sekedar sahabat.”
Mereka bertiga bertatapan lagi, benar-benar nggak bisa mengerti ucapan gue. Gue melengos dan membanting pintu dengan kesal.
“…Sampai kapanpun kalau rasinya berbeda, nggak akan ada yang mengerti.”
Dalam gelap malam, beberapa tetes air matapun jatuh dari pelupuk mata gue. Gue menggeleng pelan. Gue sadar kalau selama ini, bintang punya lajurnya sendiri-sendiri.
***
Antares, Aldebaran, Rigel
Ketiga pemuda tegap yang memilik garis wajah berbeda tersebut masih berjongkok di atas hamparan rumput segar yang basah. Di atas mereka, taburan bintang berbinar dan mengedip satu sama lain. Hanya ada satu garis unik di bagian utara, tepat di pertengahan Agustus. Itulah alasan kenapa mereka bertiga kini ada di sini.
“Al, dengerin gue. Apapun yang gue lakukan nanti, entah gue nikah sama siapa, yang jelas sebelum puncak kehidupan gue terjadi – ada lo di samping gue. Ada seorang Altair yang mudah labil dan pernah menjadi sahabat terbaik gue.” Bisik Aldebaran pelan. "Maaf ya, Al. Kita nggak tau kalau lo ternyata begitu menderita menahan rasa sakit lo. Gue nggak pernah sadar. Lo nggak pernah cerita. Kita nggak tau akhirannya bakal begini..."
“…I hate growing up…” Antares mendesis pelan. Rigel dan Aldebaran hanya berpandangan lalu merangkul Antares erat. Dalam rangkulan mereka berdua, Antares mulai sesunggukan. "Gue nggak bisa membayangkan akan jadi apa hari-hari gue tanpa lo lagi, tanpa Rigel dan Aldebaran – nggak akan ada yang ribut memilih indomie goreng atau kuah, belajar makroekonomi atau statistik duluan, ataupun sekedar berantem gonta-ganti channel televisi. Semuanya akan sepi. Bahkan sebelum mereka hilang – malam ini sudah terasa sangat sepi. Semuanya akan hilang dengan mudahnya bagai uap panas bertemu dingin."
“…Tenang aja, Al. Segala yang sudah kita lewati ini nggak akan hilang dengan mudah. Memories never fade away, they are just forgotten…” Ucap Rigel mantap. “Baik-baik ya di atas sana, Al... Gue janji, suatu saat, keempat penjaga bintang dari seluruh penjuru mata angin bisa bersama-sama lagi. Tapi kali ini adalah giliran lo, lo harus lebih dulu maju untuk membuat bintang-bintang kita semua. Karena hanya lo, bintang kita satu-satunya..."
“…I hate growing up…” Antares mendesis pelan. Rigel dan Aldebaran hanya berpandangan lalu merangkul Antares erat. Dalam rangkulan mereka berdua, Antares mulai sesunggukan. "Gue nggak bisa membayangkan akan jadi apa hari-hari gue tanpa lo lagi, tanpa Rigel dan Aldebaran – nggak akan ada yang ribut memilih indomie goreng atau kuah, belajar makroekonomi atau statistik duluan, ataupun sekedar berantem gonta-ganti channel televisi. Semuanya akan sepi. Bahkan sebelum mereka hilang – malam ini sudah terasa sangat sepi. Semuanya akan hilang dengan mudahnya bagai uap panas bertemu dingin."
“…Tenang aja, Al. Segala yang sudah kita lewati ini nggak akan hilang dengan mudah. Memories never fade away, they are just forgotten…” Ucap Rigel mantap. “Baik-baik ya di atas sana, Al... Gue janji, suatu saat, keempat penjaga bintang dari seluruh penjuru mata angin bisa bersama-sama lagi. Tapi kali ini adalah giliran lo, lo harus lebih dulu maju untuk membuat bintang-bintang kita semua. Karena hanya lo, bintang kita satu-satunya..."
Mereka bertiga memandang jauh ke atas langit gelap, dimana rasi Aquila di mata angin utara sedikit bersinar. Jauh di ujung rasi, ada sebuh bintang yang bersinar dan diam dalam langit bulan Agustus. Rasi Aquila, bintang Altair.
"When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you... If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star as dreamers do..."
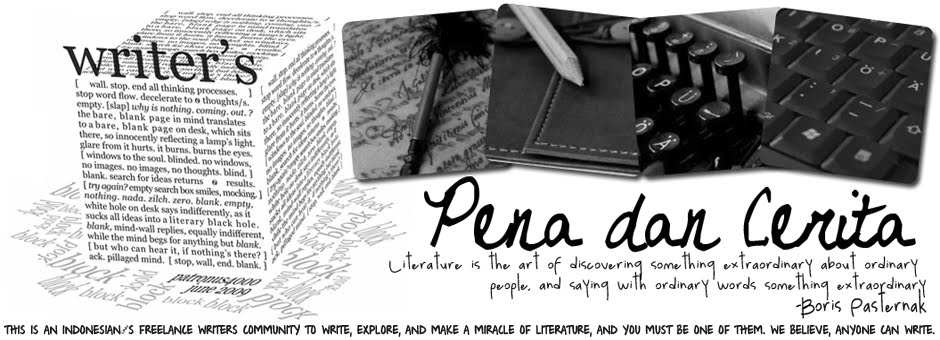

No comments:
Post a Comment