Fantasy love is much better than reality love. Never doing it is very exciting. The most exciting attractions are between two opposites that never meet.
- Semua tentang cinta. Cerita fiksi maupun non fiksi tentang bagaimana sapuan sayap kupu-kupu bergerak halus membersihkan kedengkian, bagaimana jantungmu sering menggoda rona pipi sehingga menyaingi tomat ranum, atau bagaimana seseorang yang bahkan memiliki banyak kekurangan dapat berhasil membuatmu susah makan dan tidur. Kisah-kisah itu. Kisah-kisah yang tidak masuk akal – terlalu fantasi, sayangnya kisah-kisah tersebut masuk kategori romance, bukan fantasy.
Jangan menuduh saya sarkatis.
Menjelang ulang tahun saya yang ke-25, saya semakin berpikir ulang tentang analogi kisah klasik yang sudah dipupuk sejak zaman Shakespeare. Mulai dari Romeo & Juliet, Othello, dan semakin berkembang ke Pride & Prejudice, Sense & Sensibility, sampai sekarang. Nama Nora Roberts, Stephenie Meyer, dan konco-konconya yang membuai kita dengan kisah cinta. Penulis-penulis yang cukup saya kagumi, sementara terkadang saya terlalu memikirkan apa yang mereka tulis.
Para pembaca seringkali menanyakan tentang bagaimana saya bisa mendapatkan ilham tentang seseorang yang terus-menerus mempertanyakan realita asli; sebuah cinta yang membutuhkan logika. Penuangan ilham tersebut memang dianggap sangat mengalir, lancar, dan mengena di hati. Dan bentuknya terdiri dari berbagai macam perspektif yang mengacu pada satu tema: mempertanyakan keaslian cinta sejati. Lucunya, saya seringkali menggambarkan melalui diri saya sendiri. Dengan jiwa-jiwa yang terus terpendam dalam diri saya, saya melukiskan pertanyaan yang tak terjawab itu di dalam buku.
“Lea?”
“Masuk aja,” Sahut saya. Saya menutup layar laptop, tidak mau ambil resiko kalau-kalau ada seseorang yang berhasil membaca “curhat” picisan. Hmm… curhatkah? Entah kenapa, saya suka membuat sebuah curhat yang terkesan formal. Gaya seperti itu bisa meminimalisir definisi ‘curhat’ yang terkesan cheesy banget.
“Ada yang dateng. Itu, si editor baru,” Kepala Etta menyembul dari balik pintu kerja.
Saya beranjak dari sofa nyaman, sofa yang memang khusus dipesan dalam rangka membuat kegiatan bekerja – ralat, menulis – menjadi lebih… tidak terlalu kaku. Setidaknya kalau penulisnya sudah berhati kaku, jangan sampai sofanya ikut-ikutan keras. Baru saja saya membuka pintu, mata saya terpaku pada siluet tegap yang sedang memperhatikan guci Libya warisan nenek yang terbuat dari ukiran khas renaissance. Di sisi lain, siluet itu berbalik dan ikut menatap saya heran.
“Lea?”
Damn it, Ra. Please, don’t call my name with a question mark. Seems like you are not willing to see me, to admit that I’m a real creature…
“Ini beneran Lea?”
…And that’s what I mean…
“Hei,” Akira menghampiri saya dengan senyum lebar yang selalu ia tampilkan, masih dengan garis yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Dalam jangka waktu dimana saya tidak sengaja melihatnya mengikuti turnamen kendo di daerah Kemang. Senyumnya tidak berlebihan, sekilas terlihat sinis – hanya saja ada keramahan yang sirat dalam anugerah fisik oknum satu itu. Dan saya benci untuk menyukainya, menyukainya membuat segala sesuatu terasa lebih sakit dari seharusnya. Sama sakitnya seperti ketika saya membaca ulang segala novel dan cerita buatan saya sendiri – angan-angan hampa, terlalu membuai dengan kekonyolan bualan akan sesuatu yang berakhir indah. “Aku nggak sangka kalau kantor menugasiku untuk jadi editormu. Bisa-bisanya aku nggak menduga kalau penulisnya kamu. Habis namanya beda… Dinika Leona?”
Saya mengangguk, berusaha ramah dan menyingkirkan segala sifat nyinyir yang sering sekali muncul apabila berhadapan dengan Akira. Mungkin itu salah satu luapan dan balasan atas semua impian belaka? Bahwa Akira memang hanya bayangan, segala ilusi mimpi yang indah seperti para tokoh dalam cerita? “Yah, pen name.”
Damn it, Ra. Please, don’t call my name with a question mark. Seems like you are not willing to see me, to admit that I’m a real creature…
“Ini beneran Lea?”
…And that’s what I mean…
“Hei,” Akira menghampiri saya dengan senyum lebar yang selalu ia tampilkan, masih dengan garis yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Dalam jangka waktu dimana saya tidak sengaja melihatnya mengikuti turnamen kendo di daerah Kemang. Senyumnya tidak berlebihan, sekilas terlihat sinis – hanya saja ada keramahan yang sirat dalam anugerah fisik oknum satu itu. Dan saya benci untuk menyukainya, menyukainya membuat segala sesuatu terasa lebih sakit dari seharusnya. Sama sakitnya seperti ketika saya membaca ulang segala novel dan cerita buatan saya sendiri – angan-angan hampa, terlalu membuai dengan kekonyolan bualan akan sesuatu yang berakhir indah. “Aku nggak sangka kalau kantor menugasiku untuk jadi editormu. Bisa-bisanya aku nggak menduga kalau penulisnya kamu. Habis namanya beda… Dinika Leona?”
Saya mengangguk, berusaha ramah dan menyingkirkan segala sifat nyinyir yang sering sekali muncul apabila berhadapan dengan Akira. Mungkin itu salah satu luapan dan balasan atas semua impian belaka? Bahwa Akira memang hanya bayangan, segala ilusi mimpi yang indah seperti para tokoh dalam cerita? “Yah, pen name.”
“Nggak sangka kamu kerja di MataHati. Ah bukan,” Akira menggeleng kecil. Garis keturunan Jepangnya masih sangat kontras dengan kulit Akira yang lebih gosong dari terakhir kali saya menemuinya. “Nggak sangka kalau ‘Dinika Leona’ itu kamu, teman kuliah yang paling diam. Orang yang sama dengan pendengar setiaku setiap kali ada waktu senggang untuk main ke Kantin Sastra. Dan Dinika Leona itu ternyata… salah satu temanku!”
Saya sedikit heran mendengar ucapannya yang seakan begitu mengagumi ‘Dinika Leona’ – sosok yang tak pernah ada. Seorang penulis yang tulisannya begitu lincah dan bersemangat, begitu mengikuti dinamika kehidupan. Seorang penulis yang merupakan karya seorang penulis – Lea Syofian. Dinika Leona benar-benar menyihir para pembacanya dengan pernyataan ‘The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before’. Memberi mantra dan memvisualisasikan ciri khas tokoh yang selalu beranggapan ‘nothing to lose when you know who do you want to love’.
Kenyataannya? Ha. Mencintai seseorang membuat saya kehilangan segalanya. Semuanya palsu, bahkan Dinika Leona sendiri.
“Kamu tau nggak sih, aku sudah suka banget sama novel-novelnya Dinika – maksudku, kamu – sejak lama. Sejak debut novel pertamanya: Tahun. Benar-benar melambangkan sesuatu yang sedih, tapi api semangatnya tidak pernah mati. Menunjukkan bahwa keajaiban selalu ada setiap hari. Hebat sekali kamu, Lea!” Cerocos Akira, tidak memedulikan bahwa saya tidak memberi respon. “Oh iya, sebagai editor baru, aku harus mengenali dulu cara pandang penulisanmu. Boleh?”
“Ya, ya. Tentu,” Suara saya sedikit bergetar, tanpa saya tau sebabnya. Saya menekan gagang pintu yang terasa dingin ketika menyentuh kulit. “Silakan masuk.”
“Terimakasih,” Akira langsung menghempaskan dirinya di sofa besar. “Jadi… sebenarnya apa alasan kamu untuk menulis novel?”
Tanpa tedeng aling-aling. Batin saya dalam hati. Ciri khas Akira. Lugas, serius, terus terang, tapi dengan cara yang menyenangkan… Hei, untuk apa aku mikirin Akira begini? Saya mendeham sesaat sebelum menjawab. “You know, for me, one of the hardest things in life is having words in your heart that you can’t utter.”
“Interesting. Then?”
“But letters can utter it. Even my lips never be able to.”
“Nah, aku sudah dapat konsepnya. Tapi kenapa novel roman?”
“Aku selalu merasa ada segi lain dalam roman. Semua orang seperti haus cinta, tapi seringkali roman dianggap tidak realistis. Itulah yang membuat aku merasa ada sisi ajaib dalam cinta,” Tanpa terasa, volume suara saya menjadi lebih pelan. “Kita bisa menjadi pemimpi dan orang paling realistis dalam saat yang bersamaan. Cinta bisa begitu penuh harapan baru sekaligus menyakitkan. Cinta bisa begitu tidak nyata sekaligus terlalu riil.”
Dalam beberapa detik, saya mengintip ekspresi tertegun Akira yang sedikit asing. Matanya terpaku, sementara rautnya serius. Ia menggeleng kecil dan melanjutkan, “Kalau aku perhatikan, di tiap novel kamu, kamu selalu menulis tentang definisi cinta yang berbeda-beda. Kenapa begitu?” Dahi Akira mengerut, menatap saya tajam. “Kenapa… semuanya terlihat sendu?”
“Interesting. Then?”
“But letters can utter it. Even my lips never be able to.”
“Nah, aku sudah dapat konsepnya. Tapi kenapa novel roman?”
“Aku selalu merasa ada segi lain dalam roman. Semua orang seperti haus cinta, tapi seringkali roman dianggap tidak realistis. Itulah yang membuat aku merasa ada sisi ajaib dalam cinta,” Tanpa terasa, volume suara saya menjadi lebih pelan. “Kita bisa menjadi pemimpi dan orang paling realistis dalam saat yang bersamaan. Cinta bisa begitu penuh harapan baru sekaligus menyakitkan. Cinta bisa begitu tidak nyata sekaligus terlalu riil.”
Dalam beberapa detik, saya mengintip ekspresi tertegun Akira yang sedikit asing. Matanya terpaku, sementara rautnya serius. Ia menggeleng kecil dan melanjutkan, “Kalau aku perhatikan, di tiap novel kamu, kamu selalu menulis tentang definisi cinta yang berbeda-beda. Kenapa begitu?” Dahi Akira mengerut, menatap saya tajam. “Kenapa… semuanya terlihat sendu?”
Tidak ada jawaban.
Saya sangat ingin menjawab sekarang juga; “Itu karena hari-hariku sendu sejak jatuh cinta padamu!”. Tapi untuk apa menjelaskan tentang gayung yang tidak bersambut? Untuk apa menjelaskan cintamu pada seseorang yang tidak mencintai kamu? Untuk apa menjelaskan sebuah kenyataan pahit yang mengubah setengah hidupmu hanya untuk menunggu yang bahkan tidak tau kamu menulis untuknya? “It is only a step from boredom to disillusionment, which leads naturally to self-pity, which in turn ends in chaos.”
“Ha-ha. Very funny.” Balas Akira dengan senyum mengejek. “Justru aku merasa kisah yang kamu tulis terlalu riil. Begini saja, coba aku lihat sinopsis dan kata pengantar salah satu bukumu. Hmm… kamu katanya mau nerbitin novel baru kan?”
“Yap. Sudah selesai aku edit, aku print dulu ya,” Saya buru-buru meraih laptop dan melanjutkan tulisan kata pembuka saya di softcopy novel tersebut. Nafas saya terasa berat untuk harus kembali menorehkan apa yang sebenarnya saya lalui ketika menulis. Karena Akira, semua bermula pada Akira. Dan kini… apakah berakhir pada Akira juga? Apa maksudnya hingga Akira harus menjadi editor saya?
Dalam diri saya, saya selalu ingin kisah-kisah itu terjawab dengan cepat. Walaupun jawabannya pahit, setidaknya itu akan membuat saya berhenti melarikan diri dari kenyataan bahwa kisah saya tidak bisa terjawab. Sampai kapanpun, penjelasan saya tidak akan bisa terdengar.
Menulis merupakan sumber luapan saya, dimana saya mengawali segala titian dan lumpuh – mengarungi suatu samudera diamuk badai bernama cinta. Tempat saya bisa bicara pada orang tuli, mendengar suara orang bisu, berlari bersama orang lumpuh, dan menunjukkan pelangi pada orang buta. Segala cacat itu ada pada saya, hingga saya mendapatkan inspirasi. Dan menulis menjadi pelarian bagi saya dari segala kesedihan. Memiliki pelarian nggak selamanya buruk, andai kamu mau belajar menyukai yang selama ini kamu anggap buruk.
Tulisan-tulisan memang menginspirasi, tapi tulisan-tulisan juga merupakan inspirasi.
Serta tambahan butir-butir harapan. Selama kita masih berani berharap.
Saya mencetak lembaran kertas berisikan kata pengantar dan sinopsis dengan cepat. Setelah Akira mengamati dari balik kacamatanya, ia menarik nafas. “Indah sekali.”
“Indah apanya?” Saya mendengus keki. “Indah? Sedih begitu indah?”
“Tentu saja ini indah,” Potongnya seraya melepas kacamata dari pangkal hidung. “Aku memang nggak salah baca. Selama ini aku baca tulisanmu dengan cermat, aku hanya punya satu kesimpulan. Tulisanmu adalah murni adanya. Jujur dan lancar.”
“Ck.” Gumam saya melecehkan. “Jujur? Berarti kamu kurang cermat, Ra. Kamu tau, segala tulisanku itu hanya semacam impian yang tidak pernah terjawab.”
“Tapi itu benar-benar murni impian kamu. Impian kamu yang sejujurnya. Bahwa selama ini kamu terus menunggu dan mencari definisi cinta kamu sendiri. Kejujuran adalah salah satu hal yang paling sulit dideskripsikan,” Akira mengerjap bersemangat. “Aku salut.”
“Salut? Simpan saja salutmu itu, Ra. Untuk apa…”
“Ada hal yang menarik,” Potongnya lagi. “Kamu bilang, one of the hardest things in life is having words in your heart that you can’t utter. And what is… the other thing? They are ‘things’, so it must be plenty right?”
Diam-diam, saya menggigit bibir bagian bawah pelan. Akira begitu kritis, sifat yang selalu saya sukai terhadap seseorang. Tapi dalam kasus ini, saya membencinya.
They are only two hardest things in my life. And the second is – speaking about truth – admit the truth that I love you. And it’s beautiful. Even there’s no answer… yet.
“Boleh aku tambahkan nggak halamannya?”
“Untuk apa?”
“Sejenis ucapan ‘halo’ kepada para pembaca.” Saya memutar kedua bola mata, berusaha mencairkan suasana.
“Tentu saja. Nanti langsung kirim ke penerbit,” Akira menyunggingkan senyumnya lagi dan larut dalam naskah novel saya. Saya kembali duduk di hadapan laptop dan menarik nafas. Lama. Siap menuangkan segala yang sudah terpendam. Harta yang hilangpun harus digali.
Saya nggak mau kehilangan perasaan ini, ini adalah salah satu harta berharga yang terpendam terlalu lama. Jangan sampai… orang lain menemukannya. Jangan selain Akira.
Cinta itu kadang muncul ketika
Kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya
Ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menungguinya penuh harap
Ketika ia mulai mencintai orang lain dan kamu tidak bisa berpaling
Bagaimana kamu akan berkata selamat tinggal kepada seseorang yang tidak pernah kamu miliki?
Kenapa tetes air mata jatuh demi seseorang yang tak pernah jadi kepunyaanmu?
Kenapa kamu mencintai seseorang yang cintanya tak pernah untukmu?
Cinta itu… secara fisik, sangat kecil. Hanya ada di tempat yang tidak terlihat.
Tapi sesuatu yang kecil dapat melakukan hal besar apabila ia tidak tahu bahwa dirinya kecil.
Tapi sesuatu yang tidak tahu kata kalah, tidak akan berhenti berjuang untuk menang.
Tapi sesuatu yang tidak berharap akan balasan, akan dapat tersampaikan.
Many people afraid to love without receiving any.
And I don’t want to be one of them.
And I don’t want to be one of them.
23 Juni 2010 Karya Keenam: Sebuah Novel, “TITIAN HATI”
Buku ini dipersembahkan untuk Akira Okazaki
Selalu dan selamanya, 12 tahun menjadi titian hati
Dan tetap menjadi bintang yang terkecil yang memiliki sinar paling terang
Sumber inspirasi yang tidak pernah ada batasnya
Buku ini dipersembahkan untuk Akira Okazaki
Selalu dan selamanya, 12 tahun menjadi titian hati
Dan tetap menjadi bintang yang terkecil yang memiliki sinar paling terang
Sumber inspirasi yang tidak pernah ada batasnya
***
To be continued...
Oleh: Kezia Gabriella Agusta
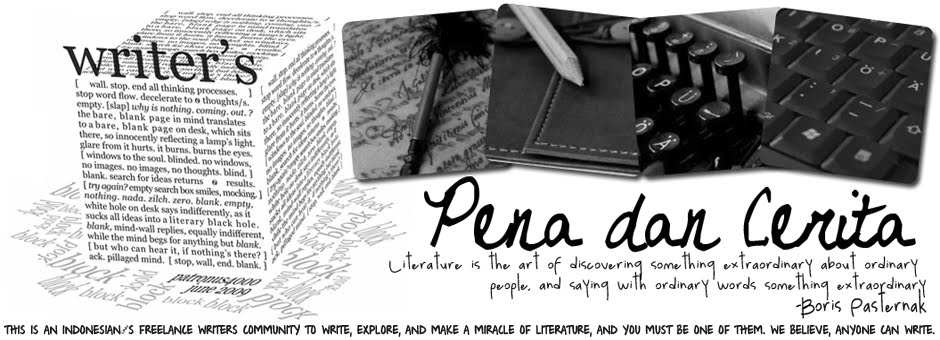

cool! :D
ReplyDelete