"Kasih gue apapun. Hansaplast, betadine, pembalut..."
"Softex maksud lo?"
Dengan penuh determinasi dan jengkel, Hilda langsung menabok lengan Ghian penuh semangat. Mata Hilda melotot bulat-bulat. "Ghi, gue serius!"
"Hahaha! Gitu aja ngambek... Hil, gimana kalau pakai Obat Batuk Hitam?"
Hilda kembali melengos. Lengosan yang terdiri dari luapan macam-macam rasa; kesal, jengkel, keki, mau ngamuk, dan rasa sedih yang begitu mencekat. Perih. Tidak menusuk, tapi menyayat dalam secara perlahan, membiarkan darah Hilda tercecer - membiarkan Hilda semakin merasakan... Eh, ini kok jadi bicarakan soal luka. Tapi memang benar, Hilda masih keki dengan insiden Ghian yang tanpa sengaja menyiram minyak panas ke lengan kiri Hilda. Dalam sekejap, kulit Hilda langsung melepuh dan Ghian pontang-panting mencari odol sampai mentega (Yang menurut Hilda nggak masuk akal, dikira lengannya roti bakar).
"Ini kalau dikasih selai kacang enak kali ya, Hil," Tambah Ghian seraya mengoleskan mentega di tangan Hilda.
"GHIAN!"
"HAHAHA! Deuh, selera humor lo bener-bener buruk ya!"
"Lagian gue masih nggak nangkep deh," Hilda mendumal kesal. "Dalam rangka apa sih SEORANG GHIAN MASAK?! Demi apa? Biasa kan lo cuma pacaran sama komputer, selingkuh sama
"Gue lagi menunaikan tugas mulia kok malah diejek tukang selingkuh."
"Lagian kenapa sih emangnya? Pembantu lo pulang kampung?"
"Nggak. Memang lagi kepengin masak aja."
"Eh, nggak cukup ya gue ngeliat muka lo tiap hari dari jendela sebelah selama 15 tahun tetanggaan? Gue udah tau kali, dimana-mana kata 'kepingin' lo itu digunakan dalam rangka 'kepingin'
Bukannya membantah, Ghian ganti tertawa halus. Cara tawanya gemulai dan sangat lembut - nggak heran kalau banyak teman sekolahnya yang suka mengejek Ghian sebagai laki-laki nggak tulen, alias agak susah menyukai perempuan. Ghian memang sudah berumur 18 tahun, tapi untuk urusan pacar? Sekalipun dalam 18 tahun belum pernah.
"Ghi?"
"Nah, udah beres nih, Hil." Potong Ghian. "Tinggal dianginin aja."
"Dianginin? Lo kira tangan gue jemuran?"
"Hil, jangan bawel kenapa? Udah ikut gue aja."
"Lho, kemana, Ghi? Ghi? Ghian!"
Terpontang-panting, Hilda mengikuti langkah Ghian yang menaiki tangga dengan cepat. Ghian membawa Hilda ke loteng rumahnya, tepat di atas genteng rumah Ghian yang berwarna jingga tua dan tertata rapi. Hilda suka suasana loteng rumah Ghian yang ditanami tumbuhan pot, dihiasi angin sepoi, serta kursi lebar di pojok.
"Ke atas genteng?"
"Udah, duduk aja sini Hil."
"Kenapa sih, Ghi?" Hilda mengambil tempat di sebelah Ghian dan langsung duduk.
"Hil..." Ghian masih menatap langit malam yang gelap dan penuh bintang dengan tatapan menerawang. "Menurut lo, buat apa sih ada waktu?"
"Waktu..." Dalam hening, Hilda ikut memelankan volume suaranya. "Waktu... tergantung bagaimana kita bisa ngaturnya sih."
"Ngatur?"
"Iya, ngatur aja gimana. Kapan lo mau makan, mau mandi, mau belajar..." Jawab Hilda asal, membuat Ghian langsung memelototinya. Ia meringis geli. "Oke, serius. Waktu itu... mengikuti alur kehidupan. Untuk yang menungguinya, waktu terasa lambat. Waktu terlalu melonjak bagi yang takut akan waktu. Terlalu lama bagi yang mudah bosan. Terlalu pendek bagi yang mensyukurinya." Ucap Hilda pelan. "Tapi bagi yang mencintainya, waktu adalah selamanya."
Ghian menarik nafas. Singkat, tapi helaannya berat. "Menurut lo, buat apa sih ada lo di dunia ini?"
"Gue?" Alis Hilda naik beberapa senti. "Mungkin... Untuk tau bahwa ada spesies aneh kayak gue. Satu hal aja sih yang gue tau, gue ada di sini untuk hidup bagi orang lain. Orang lain di luar sana yang entah siapapun namanya."
"Nah, udah beres nih, Hil." Potong Ghian. "Tinggal dianginin aja."
"Dianginin? Lo kira tangan gue jemuran?"
"Hil, jangan bawel kenapa? Udah ikut gue aja."
"Lho, kemana, Ghi? Ghi? Ghian!"
Terpontang-panting, Hilda mengikuti langkah Ghian yang menaiki tangga dengan cepat. Ghian membawa Hilda ke loteng rumahnya, tepat di atas genteng rumah Ghian yang berwarna jingga tua dan tertata rapi. Hilda suka suasana loteng rumah Ghian yang ditanami tumbuhan pot, dihiasi angin sepoi, serta kursi lebar di pojok.
"Ke atas genteng?"
"Udah, duduk aja sini Hil."
"Kenapa sih, Ghi?" Hilda mengambil tempat di sebelah Ghian dan langsung duduk.
"Hil..." Ghian masih menatap langit malam yang gelap dan penuh bintang dengan tatapan menerawang. "Menurut lo, buat apa sih ada waktu?"
"Waktu..." Dalam hening, Hilda ikut memelankan volume suaranya. "Waktu... tergantung bagaimana kita bisa ngaturnya sih."
"Ngatur?"
"Iya, ngatur aja gimana. Kapan lo mau makan, mau mandi, mau belajar..." Jawab Hilda asal, membuat Ghian langsung memelototinya. Ia meringis geli. "Oke, serius. Waktu itu... mengikuti alur kehidupan. Untuk yang menungguinya, waktu terasa lambat. Waktu terlalu melonjak bagi yang takut akan waktu. Terlalu lama bagi yang mudah bosan. Terlalu pendek bagi yang mensyukurinya." Ucap Hilda pelan. "Tapi bagi yang mencintainya, waktu adalah selamanya."
Ghian menarik nafas. Singkat, tapi helaannya berat. "Menurut lo, buat apa sih ada lo di dunia ini?"
"Gue?" Alis Hilda naik beberapa senti. "Mungkin... Untuk tau bahwa ada spesies aneh kayak gue. Satu hal aja sih yang gue tau, gue ada di sini untuk hidup bagi orang lain. Orang lain di luar sana yang entah siapapun namanya."
"Orang lain?" Ghian menelan ludah. Pahit. "Pasangan hidup?"
"Pasangan hidup? Buset. Dikira gue mikir sampai sejauh itu ya."
"Terus apa dong? Belahan jiwa?"
"Mungkin. Gue selalu percaya kalau tiap manusia memiliki pecahan dirinya yang terlahir berbeda. Gue percaya itu."
"Ohh..." Gumam Ghian. "Terus menurut lo, buat apa sih ada gue di dunia ini?"
"Hah?" Hilda menatap Ghian nyureng. "Lo kesetanan apa sih?"
"Jawab aja, Hil. I need answer."
"Kenapa lo ada? Jujur ya, gue pengin jawab 'Meneketehe, apa urusan gue' - tapi kok kesannya kejam banget." Ucap Hilda cuek. Buru-buru ia meralat ketika melihat Ghian sudah memelototinya jutek. "Yaaa... apa sih? Lo hidup baik-baik begitu, doyan mengautis di kamar, ngutak-ngatik komputer gue sembarangan, buat apa ya?"
Hilda benar-benar tidak tau jawabannya. Blank. Tapi Ghian masih ngotot meminta jawaban dengan tatapan menunggu.
"Ghian itu ada... hmm... mungkin," Hilda menelan ludah. "Supaya bikin gue bisa tidur tiap malam?"
"Eh?"
"Yah..." Wajah Hilda menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. "... Jujur aja, kalau tiap malam lo nggak buka jendela terus main gitar di pinggir jendela, gue suka merasa tidur gue nggak tenang."
"Pasangan hidup? Buset. Dikira gue mikir sampai sejauh itu ya."
"Terus apa dong? Belahan jiwa?"
"Mungkin. Gue selalu percaya kalau tiap manusia memiliki pecahan dirinya yang terlahir berbeda. Gue percaya itu."
"Ohh..." Gumam Ghian. "Terus menurut lo, buat apa sih ada gue di dunia ini?"
"Hah?" Hilda menatap Ghian nyureng. "Lo kesetanan apa sih?"
"Jawab aja, Hil. I need answer."
"Kenapa lo ada? Jujur ya, gue pengin jawab 'Meneketehe, apa urusan gue' - tapi kok kesannya kejam banget." Ucap Hilda cuek. Buru-buru ia meralat ketika melihat Ghian sudah memelototinya jutek. "Yaaa... apa sih? Lo hidup baik-baik begitu, doyan mengautis di kamar, ngutak-ngatik komputer gue sembarangan, buat apa ya?"
Hilda benar-benar tidak tau jawabannya. Blank. Tapi Ghian masih ngotot meminta jawaban dengan tatapan menunggu.
"Ghian itu ada... hmm... mungkin," Hilda menelan ludah. "Supaya bikin gue bisa tidur tiap malam?"
"Eh?"
"Yah..." Wajah Hilda menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. "... Jujur aja, kalau tiap malam lo nggak buka jendela terus main gitar di pinggir jendela, gue suka merasa tidur gue nggak tenang."
"Oh, jadi lo rupanya suka diem-diem ngintip gue main gitar ya." Kata Ghian mesem-mesem.
"Jangan GR deh!"
"Halah, ngaku aja!"
"Oke, oke, emang iya. Tapi lo juga gak usah ke-GR-an! Bukan berarti gue suka juga permainan gitar lo."
"Kalau gak suka kok diliatin melulu," Ghian mencibir.
"Tapi kalau nggak ada lo ya, Ghi, gue nggak bisa jadi kayak begini."
"Begini gimana? Bawel? Nyebelin? Rese? Suka nggak penting? Wah, itu sih bukan gara-gara gue. Cacat lahir itu mah."
"Batek ye lo! Maksud gue, begini... bisa ngertiin orang lain. Gue belajar toleransi juga dari lo. Inget kasus waktu kita masih kelas 6 SD? Yang waktu Jia Pei - anak baru pindahan dari Cina itu, jadi bahan olok-olok anak satu sekolah karena rasnya beda?"
"Inget kok. Kenapa?"
"Gue dulu juga pernah nge-bully dia."
Ghian langsung tersedak. "BULLY?"
"Iya, ngegencet. Tapi inget nggak waktu itu, apa pendapat lo soal Jia Pei?"
Dahi Ghian mengerut heran. "Memang apaan?"
"Lo bilang 'Perbedaan justru bikin kita kuat. Perbedaan pikiran akan menambah ide, perbedaan kekuatan akan menambah tenaga, perbedaan latar belakang akan menambah tenggang rasa yang seringkali hilang'. Lo ngomong begitu..." Kata Hilda. "Sejak itu, gue selalu merasa kalau memang benar, Ghian itu ada untuk merubah sesuatu. Salah satunya... merubah gue."
Ghian tidak merespon. Ia tetap memandang langit yang terbentang tanpa garis tepian dengan senyum di bibirnya. "Jadi gue ada buat lo?"
"Mungkin."
"Kok mungkin sih?"
Hilda menatap Ghian makin nggak ngerti. Ia menatapi kedua mata sendu di hadapannya penuh tanda tanya. "Yaa... oke, pasti. Pasti Ghian itu ada buat gue."
"Syukurlah."
Ghian kembali diam. Sayup-sayup diam miliknya diisi oleh para jangkrik serta kerlip bintang di kala mentari sudah enggan bersinar. Gelap. Tapi biasanya gelap malampun tidak segelap ini.
Gelap ini seakan enggan untuk menjadi terang kembali. Dan selamanya akan terus begitu.
***
"Elo masih aja ya, tiap minggu ke sini melulu."
"Eh, Rian." Hilda tersenyum dan mengusap pipinya yang basah. "Ngapain ke sini?"
"Menurut lo gue ngapain?"
Dahi Hilda mengerut lucu, pura-pura berpikir padahal ia sudah tau jawabannya. "Hmm... nengokin nenek lampir?"
"Ooh... Jadi lo ngaku sebagai nenek lampir ya. Habisnya gue ke sini buat nengokin lo, tuh."
Hilda tertawa lepas, menanggapi guyonan Rian yang berusaha mengenyahkan pikiran sedih di pojok hatinya. Tawa Hilda lama-lama larut kembali dalam tatapannya yang menerawang.
"...Sudah setengah tahun ya, Yan..."
"Iya," Sahut Rian. "Nggak ada yang sangka kalau ia akan pergi secepat itu."
"Dan bahkan gue - sahabatnya dan tetangganya - nggak tau soal operasi maupun penyakitnya," Ucap Hilda getir. "Gue nggak tau... kalau pembicaraan asal di genteng rumahnya waktu itu akan jadi masa-masa terakhir gue. Gue nggak tau kalau diamnya waktu itu akan jadi diam paling berisik yang pernah ada. Kenapa gue harus tau terlambat?"
"Yang terlambat bukan untuk disesali, Hil."
"Tapi ini Ghian, Yan. Bukan kucing tetangga!" Hilda mulai menangis lagi, menatapi nisan penuh ukiran di depannya miris. "Ini bukan soal teman sehari gue. Dia teman gue selama 15 tahun. Dan kenapa gue harus kehilangan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal? He is the one, Yan. He's the one..."
Rian meringis, menyadari bahwa perasaannya pada Hilda memang sampai kapanpun tidak akan pernah terbalas. Ia merangkul Hilda yang sudah bersujud lemas di depan nisan Ghian. "Ssh... Gue tau, lo sayang sama dia..."
"...He's the one who kept me alive like this..."
Rian mengangguk sedih. "Gue ngerti. Nah, jangan nangis lagi ya, Hil. Dan kata-kata lo salah. Bukan 'selamat tinggal', tapi 'sampai jumpa lagi'." Tambah Rian lembut. Ia menepuk kepala Hilda pelan. "Dan nggak ada yang terlambat. Lo bisa ngucapin itu sekarang. Bicara pada Ghian, Hil - bicara seperti wajahnya ada di hadapanmu."
Rian beranjak pergi meninggalkan Hilda yang sendirian, sesunggukan menatapi kuburan Ghian. Ia menelan ludah. "Ghi..."
Tidak ada jawaban.
"...Gue tau, Ghi, mungkin gue memang bodoh banget masih berharap mendengar suara lo. Bahkan di saat lo sudah nggak ada di dunia ini. Nonsense memang, tapi lebih baik gue bicara daripada tidak sama sekali." Hilda menarik nafas panjang. "Gue sayang sama lo. Atau lebih tepat... gue cinta sama lo."
Tidak ada jawaban.
"...Sebenarnya masih banyak kata-kata yang tertinggal, yang nggak bisa gue ucapin, Ghi. Tapi setiap hari gue nggak pernah berhenti berharap agar lo tau. Tapi tolong, Ghi, kasih tau gue..." Mata Hilda mulai berkaca-kaca lagi, suaranya kembali sengau. "...Kasih tau gue bagaimana caranya bicara sama lo lagi, kasih tau gue bagaimana caranya agar gue nggak nangis lagi... Gue nggak pernah nyangka kalau semuanya bakal begini. Setau gue lo itu kuat - sehat, rajin olahraga lagi. Gue nggak pernah berpikir kalau orang yang selama ini ada di samping gue akan hilang selamanya..."
Angin berhembus kencang, membuat Hilda sedikit menggigil. Ia menatapi nisan Ghian sedih. Perlahan, Hilda meraih nisan tersebut dan memeluknya erat - membiarkan nisan itu mendapat kehangatan. Jemari Hilda meraih bagian belakang nisan tersebut. Dengan cepat, Hilda langsung mengintip sesuatu yang ia sentuh tadi - sesuatu yang memiliki lekukan.
Ukiran.
Mata Hilda masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya cepat dan membacanya berulang. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali...
"Ghi..." Hilda menutup mulutnya tidak percaya. "...Ini..."
Masih tidak percaya, Hilda membacanya lagi. Berharap ukiran tersebut dapat berpindah - dapat terukir di dalam hatinya. Dan selamanya terpatri di sana.
"...Gue janji, gue nggak akan nangis lagi."
People think a soul mate is your perfect fit, and that’s what everyone wants. But a true soul mate is a mirror, the person who shows you everything that is holding you back, the person who brings you to your own attention so you can change your life.
A true soul mate is probably the most important person you’ll ever meet, because they tear down your walls and smack you awake. But to live with a soul mate forever? Nah. Too painful. Soul mates, they come into your life just to reveal another layer of yourself to you, and then leave.
A soul mates purpose is to shake you up, tear apart your ego a little bit, show you your obstacles and addictions, break your heart open so new light can get in, make you so desperate and out of control that you have to transform your life.
A true soul mate is probably the most important person you’ll ever meet, because they tear down your walls and smack you awake. But to live with a soul mate forever? Nah. Too painful. Soul mates, they come into your life just to reveal another layer of yourself to you, and then leave.
A soul mates purpose is to shake you up, tear apart your ego a little bit, show you your obstacles and addictions, break your heart open so new light can get in, make you so desperate and out of control that you have to transform your life.
Please, don't ever cry for me. - G
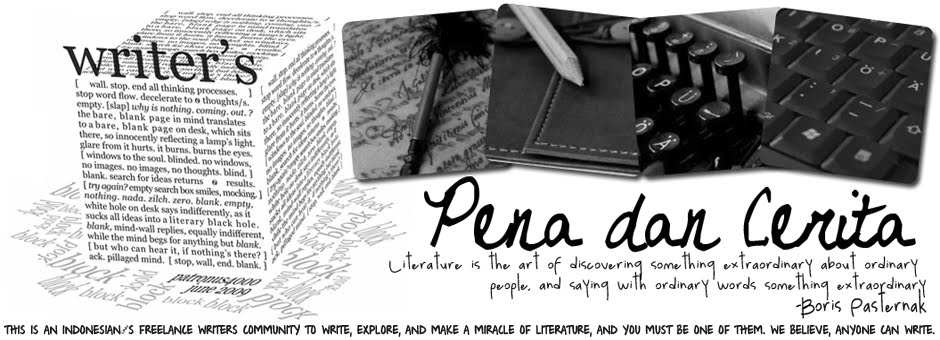

Hi!
ReplyDeleteGue baru aja blogwalking dan ngeliat blog ini, it's totally awesome ..
Ceritanya keren2 ..
Gue suka yang ini, tapi agak2 mirip sama salah satu novel lama ..
Atau gue aja yg de javu
Boleh gue taro link blog ini di blog gue ?
Sure! Thanks for reading yaa :)
ReplyDeleteboleh sedikit masukan ?
ReplyDeleteterlalu banyak direct speech hehehehehehe
tapi foto di atas genteng itu...ummmmm sangat keren hehehehe
ReplyDelete